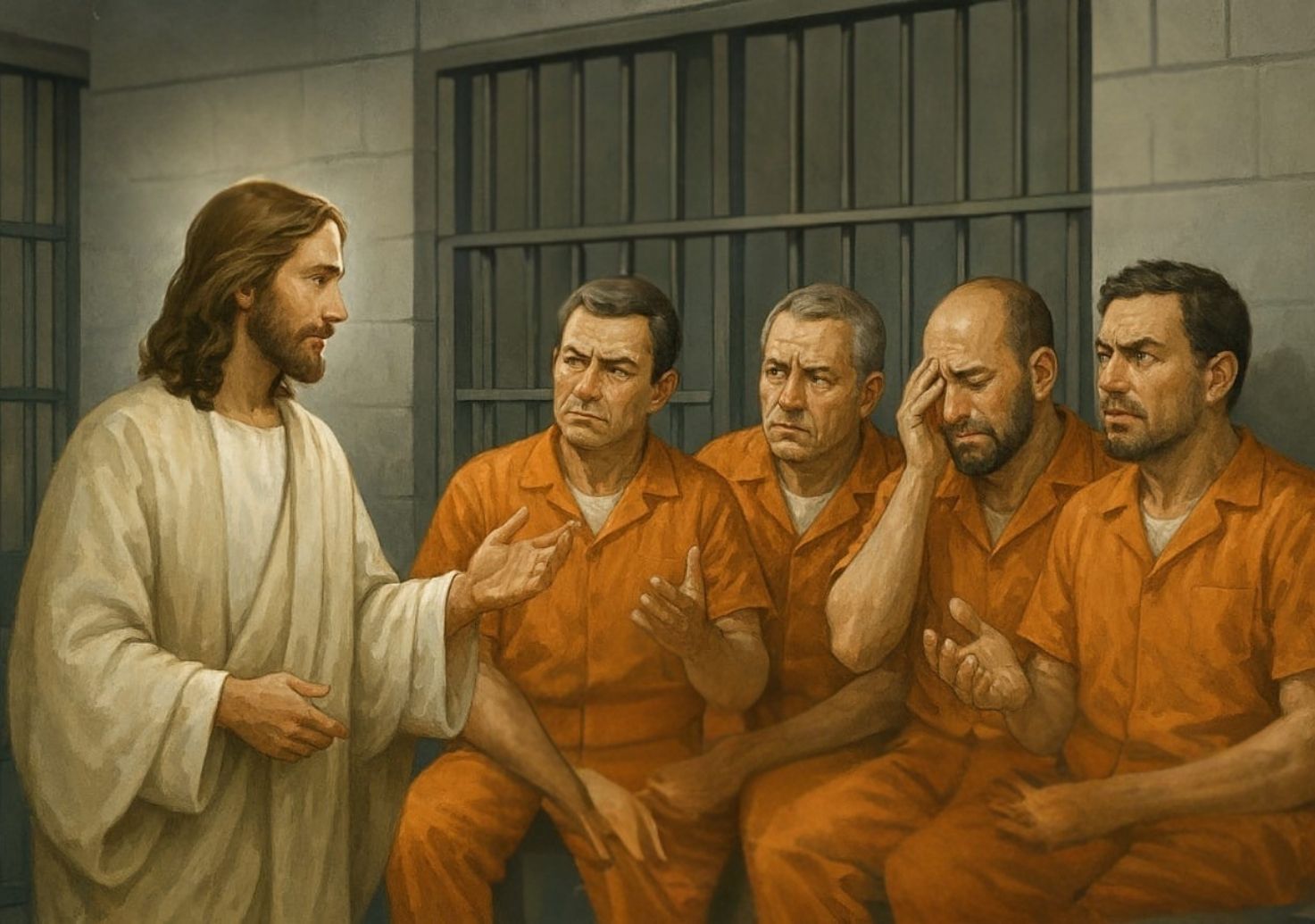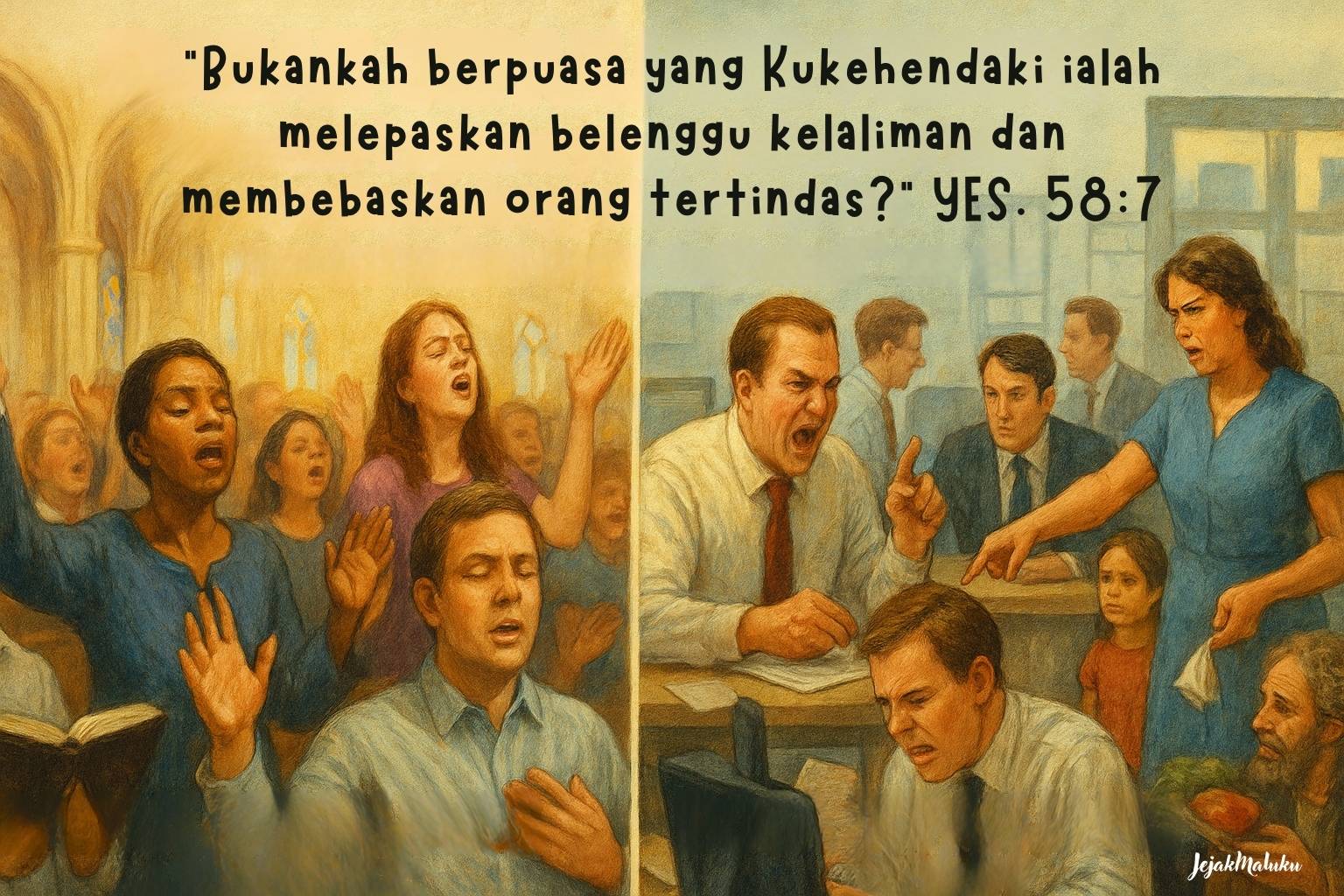Capek, ya, lihat berita? Setiap hari ada saja pejabat yang ditangkap karena korupsi. Rasanya kok tidak ada habisnya. Ada yang bilang sistemnya salah, ada yang bilang penegakan hukumnya kurang. Tapi jujur, rasanya semua alasan itu cuma basa-basi. Coba kita lihat lebih dalam, dan berani jujur pada diri sendiri. Korupsi itu bukan cuma masalah pejabat di Senayan atau bupati yang kena OTT. Korupsi itu sudah jadi budaya kita. Iya, budaya kita.
Jangan langsung marah. Pikirkan lagi.
Korupsi telah menjadi salah satu isu paling mendalam dan kronis dalam masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, fenomena ini terus muncul sebagai berita utama hampir setiap minggu. Dari perspektif reflektif, korupsi bukan sekadar tindakan individu yang menyimpang, melainkan cerminan dari budaya yang telah tertanam dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi kita. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2024, KPK telah menangani lebih dari 1.600 perkara korupsi, dengan ratusan pejabat publik terlibat, termasuk 167 kepala daerah seperti bupati dan walikota. Hal ini mengundang kita untuk merefleksikan akar masalah yang lebih dalam: apakah korupsi telah menjadi bagian dari “budaya” kita?
Korupsi Bukan Cuma Soal Uang Milyaran
Ketika kita menyuap polisi biar tidak ditilang, itu korupsi. Ketika kita kasih “uang rokok” ke petugas kelurahan biar surat-surat cepat selesai, itu korupsi. Ketika kita nitip absen kuliah atau kantor, itu juga korupsi. Kita semua terlibat dalam praktik-praktik kecil ini, seolah itu hal yang wajar dan normal. Kita bahkan punya istilahnya sendiri: “uang pelicin”, “biar lancar”, “asal sama-sama enak”.
Kita sudah terbiasa menganggap jalan pintas itu sebagai solusi. Daripada ikut antrean, lebih baik bayar lebih. Daripada ikut prosedur, lebih baik pakai “orang dalam”. Kita diajari bahwa kesabaran dan kejujuran itu ribet, dan yang penting urusan beres. Mentalitas ini yang pada akhirnya membiarkan korupsi besar-besaran tumbuh subur.
Mungkin karena kita merasa tidak berdaya. Kita tahu itu salah, tapi kita ikut melakukannya karena “semua orang juga begitu”. Kita apatis, berpikir bahwa tidak ada yang bisa diubah. “Percuma lapor, toh tidak bakal ditindaklanjuti.” “Percuma jujur, nanti malah dipersulit.”
Sikap pasrah ini yang paling berbahaya. Ketika korupsi sudah dianggap sebagai bagian dari hidup, kita kehilangan empati. Kita enggak lagi peduli bahwa uang yang dikorupsi itu seharusnya jadi jalanan yang mulus, fasilitas kesehatan yang layak, atau sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Kita cuma peduli urusan kita sendiri selesai.
Ini bukan artikel untuk menyalahkan, tapi untuk bercermin. Kalau kita mau benar-benar memberantas korupsi, mulailah dari diri sendiri. Tidak usah muluk-muluk. Tolak tawaran suap kecil. Berani bilang “tidak” pada praktik-praktik curang.
Mungkin kita tidak bisa mengubah pejabat di atas sana, tapi kita bisa mengubah diri kita dan lingkungan terdekat. Kalau kita terus-terusan menganggap korupsi adalah bagian dari budaya, kita selamanya akan terjebak dalam lingkaran setan ini.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti bilang “sistemnya salah” dan mulai bilang “kita yang salah”. Kita yang membiarkan budaya ini berlanjut.
Pakta Integritas: Antara Janji dan Realitas
Pakta integritas sering kali digembar-gemborkan sebagai benteng pertahanan melawan korupsi. Dokumen ini, yang ditandatangani oleh para pejabat, berisi komitmen untuk menjunjung tinggi etika dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, pakta ini sering kali hanya menjadi formalitas belaka. Statistik KPK mencatat bahwa meskipun ribuan pakta telah ditandatangani, jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tetap tinggi, dengan lebih dari 360 anggota legislatif dan pejabat eselon terjerat sejak 2004.
Hal ini mengajak kita bertanya: apakah pakta integritas gagal karena kurangnya penegakan, atau karena ia tidak menyentuh akar budaya yang memandang korupsi sebagai jalan pintas menuju kesuksesan? Dalam konteks ini, pakta integritas tampak seperti aksesori simbolis yang tidak mampu mengubah perilaku jika tidak didukung oleh sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat.
Dimensi Sistemik: Lebih dari Sekadar Moral Individu
Korupsi di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan moral individu. Ia adalah hasil dari sistem yang memungkinkan, bahkan mendorong, praktik tersebut. Budaya patronase, di mana loyalitas kepada atasan lebih diutamakan daripada akuntabilitas publik, menjadi salah satu pendorong utama. Selain itu, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses tender menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang. Laporan Tahunan KPK 2024 mengungkapkan bahwa sektor swasta menjadi penyumbang tersangka korupsi tertinggi, dengan 466 kasus terkait korporasi, menunjukkan bagaimana korupsi merembes ke berbagai lapisan masyarakat.
Refleksi mendalam atas hal ini mengingatkan kita bahwa reformasi harus bersifat sistemik: memperbaiki mekanisme rekrutmen pejabat, meningkatkan gaji aparatur untuk mengurangi godaan, dan memperkuat lembaga pengawas independen. Tanpa pendekatan holistik, korupsi akan terus menjadi “norma” yang diterima secara diam-diam.
Peran Masyarakat: Dari Penonton Pasif ke Agen Perubahan
Masyarakat sering kali diposisikan sebagai korban korupsi, tetapi refleksi jujur menunjukkan bahwa kita juga turut andil dalam mempertahankan budaya ini. Banyak kasus korupsi kecil, seperti pemberian “pelicin” untuk mempercepat urusan administratif, mencerminkan penerimaan sosial terhadap praktik tersebut. Sementara itu, respons masyarakat terhadap skandal korupsi sering terbatas pada kemarahan sementara di media sosial, tanpa tindakan nyata seperti pelaporan atau partisipasi dalam pengawasan. Data KPK menunjukkan bahwa dari 1.809 kasus yang ditangani berdasarkan profesi pelaku, mayoritas melibatkan aktor dari berbagai sektor, termasuk swasta dan publik, yang menandakan masalah yang meluas.
Untuk mengubah ini, masyarakat harus bertransisi dari penonton pasif menjadi agen perubahan: mendukung inisiatif transparansi, melaporkan dugaan korupsi, dan mendidik generasi muda tentang nilai integritas. Refleksi ini mengajak kita melihat cermin: apakah kita siap berkontribusi atau terus membiarkan budaya korupsi berkembang?
Menuju Solusi: Refleksi atas Harapan dan Tantangan
Solusi atas korupsi memerlukan komitmen jangka panjang. Penguatan pengawasan melalui audit independen dan teknologi digital untuk transparansi anggaran adalah langkah awal. Reformasi birokrasi, termasuk penghapusan budaya patronase dan peningkatan akuntabilitas, harus menjadi prioritas. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah mindset kolektif: dari melihat korupsi sebagai “kebiasaan” menjadi “ancaman” bagi kemajuan bangsa. Tren data KPK menunjukkan peningkatan kasus penyuapan sebagai modus utama, yang menekankan perlunya pendidikan anti-korupsi sejak dini. Ini mengharapkan bahwa dengan tekanan publik yang konsisten dan kepemimpinan yang teladan, kita dapat memutus rantai budaya korupsi.
Penutup: Membangun Budaya Integritas
Pada akhirnya, korupsi adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa. Ia bukan takdir, melainkan pilihan yang dapat diubah melalui refleksi dan aksi kolektif. Mari kita mulai dari diri sendiri: menolak segala bentuk korupsi kecil, mendukung lembaga seperti KPK, dan membangun budaya integritas yang sejati. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat maju sebagai negara yang adil dan sejahtera, bebas dari belenggu korupsi.