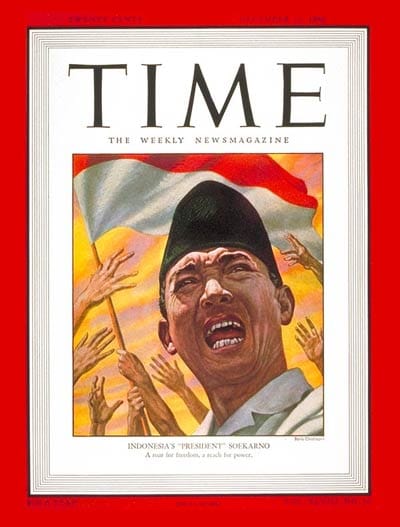Republik Maluku Selatan (RMS)
Dominasi nasionalis di DMS dan administrasi lokal tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya mengendalikan masyarakat Ambon. Hanya empat bulan setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada Desember 1949, Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan.
Proklamasi ini terjadi dalam suasana ketidakpastian politik yang besar akibat pemberontakan APRA di Jawa Barat yang dipimpin oleh Raymond Westerling serta pemberontakan Andi Aziz di Makassar.
Kelompok utama yang berada di balik proklamasi RMS terdiri dari politisi emigran seperti Ir. J. A. Manusama dan Mr. Dr. Chr. Soumokil, serta sekelompok raja, dengan dukungan serta tekanan dari tentara KNIL Ambon yang baru kembali ke Ambon dan sedang menunggu “reorganisasi” tentara kolonial.
Dalam konteks perubahan sosial yang telah dibahas dalam artikel ini, para pemimpin dan pendukung RMS berasal dari kelompok-kelompok yang telah memperoleh manfaat dari kehadiran kolonial. Mereka khawatir bahwa jika pemerintah Jakarta menguasai Ambon, status, pengaruh, dan jabatan mereka akan terancam.
Lebih jauh lagi, RMS dapat dilihat sebagai upaya kelompok-kelompok ini untuk membalikkan proses perubahan sosial yang telah terjadi selama beberapa dekade sebelumnya dan untuk (kembali) membangun posisi mereka dalam masyarakat Ambon.
Bagian selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai kelompok utama yang mendorong pembentukan RMS, termasuk peran tentara KNIL, raja, dan kaum emigran Kristen Ambon.
Kaum Emigran “Kelas Menengah”
Di antara tokoh utama dalam peristiwa yang mengarah pada proklamasi RMS adalah anggota “kelas menengah” Kristen Ambon, terutama Ir. J. A. Manusama, Mr. Dr. Chr. Soumokil, dan Alex Nanlohy. Mereka mewakili kelompok emigran Ambon yang lahir, dibesarkan, dan dididik dalam lingkungan birokrasi kolonial yang berbahasa Belanda.
Manusama melarikan diri dari revolusi di Jawa, pertama ke Makassar, lalu ke Ambon, di mana ia menjadi kepala sekolah menengah baru (Algemene Middelbare School) dan ditunjuk sebagai wakil komunitas emigran di Dewan Maluku Selatan. Soumokil sebelumnya hanya dua kali mengunjungi Ambon secara singkat sebagai Menteri dalam pemerintahan NIT sebelum ia melarikan diri ke Ambon setelah pemberontakan Andi Aziz di Makassar gagal.
Nanlohy tiba dari Jawa pada tahun 1947. Sama seperti banyak emigran sebelum mereka, mereka berusaha memainkan peran penting dalam institusi demokrasi yang baru muncul di Ambon pasca-perang. Namun, seperti halnya raja, mereka tidak memiliki pengalaman politik, keterampilan, atau organisasi yang cukup untuk bersaing dengan politisi nasionalis.
Manusama dan Nanlohy gagal memenangkan kursi dalam pemilihan Dewan Maluku Selatan kedua, meskipun mereka mencalonkan diri di dua daerah pemilihan berbeda. Manusama sendiri sadar bahwa sebagai orang luar, ia dipandang dengan kecurigaan oleh para raja. Bahkan, ia sendiri merasa canggung dan tidak memahami sepenuhnya masyarakat negeri. Ia menolak undangan dari raja untuk mengunjungi negeri asalnya, Abubu, hingga akhirnya ia dievakuasi dari Ambon ke Seram pada November 1950.
Karier politik Manusama mendapatkan momentum baru pada tahun 1949 ketika ia diangkat ke Senat NIT. Baik Soumokil maupun Manusama bukanlah pendukung organisasi loyalis atau separatis di Ambon sebelum penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Mereka baru mulai memperjuangkan kemerdekaan Maluku Selatan ketika pemerintahan NIT—yang menjadi dasar karier politik mereka—runtuh.
Dalam kepemimpinan RMS yang merdeka, mereka akhirnya memperoleh peran yang sesuai dengan status mereka di masyarakat Ambon.
Peran Tentara KNIL
Kelompok emigran lain yang memainkan peran dalam pembentukan RMS adalah para tentara KNIL Ambon. Sebelum Konferensi Meja Bundar, tentara KNIL ini hanya memiliki keterlibatan politik yang terbatas di Ambon. Meskipun kadang-kadang terjadi intimidasi terhadap para nasionalis, misalnya ketika Dewan Maluku Selatan (DMS) membahas isu-isu sensitif, tentara KNIL tidak memiliki peran politik yang signifikan.
Di luar Kepulauan Ambon, banyak tentara Ambon yang tergabung dalam organisasi seperti Ambonsch Studiefonds, dan A. J. Patty pernah mencoba menarik mereka ke dalam Sarekat Ambon. Setelah perang, dukungan tentara KNIL Ambon dimobilisasi untuk organisasi separatis seperti Persatoean Timoer Besar (PTB).
Salah satu alasan utama mengapa tentara KNIL tidak memainkan peran politik besar di Ambon adalah kebijakan Belanda yang menempatkan mereka di luar daerah asal mereka. Sebagian karena mereka lebih berguna di daerah lain, tetapi juga karena hubungan mereka dengan negeri asal mereka sering kali bermasalah.
Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan sistem status sosial. Mayoritas tentara KNIL Ambon berasal dari keluarga non-elit dalam negeri mereka. Namun, dalam KNIL, mereka diajarkan bahwa mereka memiliki bevoorrechte positie (status istimewa). Ketika mereka kembali ke Ambon sebagai “orang yang telah melihat dunia”, mereka sering kali tidak menerima pengakuan status yang mereka harapkan dari masyarakat negeri. Selain itu, pola hidup mereka yang terbentuk di dalam militer sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai tradisional di kampung halaman mereka.
Hal ini semakin diperumit oleh ketergantungan ekonomi masyarakat negeri terhadap gaji dan pensiun tentara KNIL. Dengan adanya ketidakpastian mengenai masa depan mereka setelah pembubaran KNIL, banyak keluarga yang khawatir tentang hilangnya sumber pendapatan utama mereka.
Pada akhir tahun 1949 dan awal tahun 1950, untuk pertama kalinya dalam sejarah KNIL, sekitar 2.000 tentara Ambon ditempatkan di Ambon untuk menunggu transfer ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau proses demobilisasi.
Ketika mereka kembali, mereka mendapati Ambon telah berubah drastis. Administrasi daerah kini berada di tangan orang Ambon yang mendukung Indonesia. Satu-satunya organisasi politik yang efektif—Partai Indonesia Merdeka (PIM)—mendukung Republik Indonesia, negara yang telah mereka lawan selama empat tahun terakhir. Selain itu, pemuda nasionalis yang tergabung dalam PIM melakukan latihan militer di jalanan Ambon, yang semakin memicu ketegangan dengan tentara KNIL.
Pada awalnya, tentara KNIL menjadi aktor dalam konflik politik lokal dengan mendukung raja dan kelompok separatis untuk menekan pengaruh nasionalis di negeri-negeri. Pada Januari 1950, terjadi bentrokan antara tentara KNIL dan pemuda nasionalis, tetapi setelah itu, para nasionalis mencoba merangkul mereka.
Namun, pada bulan April, para emigran Kristen seperti Manusama, Soumokil, dan Alex Nanlohy berhasil memenangkan dukungan tentara KNIL dalam upaya terakhir mereka untuk mencegah masuknya pasukan TNI ke Ambon.
Peran Para Raja
Kelompok lokal yang paling berpengaruh dalam RMS adalah para raja, baik dari negeri Kristen maupun Muslim. Sebelumnya, mereka juga merupakan inti dari organisasi separatis.
Namun, pola perubahan sosial jangka panjang menunjukkan bahwa kekuasaan para raja terus menyusut. Dalam organisasi separatis dan RMS, para raja hanya memainkan peran yang lebih kecil dan bersifat subordinatif.
Satu-satunya raja yang benar-benar berperan aktif dalam mempromosikan RMS adalah Ibrahim Ohorella, raja negeri Muslim Tulehu. Ia menyediakan tempat bagi pertemuan penting sebelum proklamasi, mengorganisir dan membawa massa ke pertemuan besar Manusama pada 18 April 1950, serta menjadi menteri dalam kabinet RMS.
D. J. Gaspersz, raja dari negeri Kristen Naku dan seorang pejabat senior dalam pemerintahan kolonial, juga dimasukkan dalam kabinet RMS. Namun, ia lebih dihargai karena pengalamannya dalam birokrasi daripada karena komitmennya terhadap gerakan RMS.
Para raja pada dasarnya mengharapkan kembalinya status quo kolonial ketika Belanda kembali setelah perang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Belanda akan benar-benar menyerahkan Ambon kepada Republik Indonesia.
Banyak dari mereka berusaha meyakinkan pemerintah kolonial Belanda bahwa mereka ingin tetap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, tetapi aspirasi mereka tidak dihiraukan.
Dalam negeri-negeri mereka sendiri, banyak raja menghadapi oposisi dari kelompok nasionalis yang semakin kuat. Di banyak tempat, raja melihat bahwa nasionalisme Indonesia sering kali terkait dengan oposisi dalam negeri mereka sendiri.
Dalam RMS, kelompok oposisi ini ditindas, dan para raja diberikan tempat dalam pemerintahan RMS. Ketika parlemen RMS dibentuk, semua raja secara otomatis menjadi anggota.
Kejatuhan RMS
Proklamasi RMS pada 25 April 1950 diikuti oleh intervensi militer dari pemerintah Republik Indonesia.
Pada 28 September 1950, pasukan TNI mendarat di Ambon dan, setelah pertempuran sengit, berhasil merebut kota pada 3 November. Sisa pasukan RMS melarikan diri ke Pulau Seram, di mana gerilya RMS bertahan hingga 1963.
Akibat dari pemberontakan RMS sangat besar bagi masyarakat Ambon.
Sebanyak 4.000 mantan tentara KNIL Ambon dan keluarga mereka diasingkan ke Belanda, di mana mereka menetap secara permanen.
Di Ambon, masyarakat mengalami perpecahan yang mendalam antara mereka yang mendukung dan menentang RMS.
Para mantan pendukung RMS mengalami diskriminasi politik dan sosial, sementara para pemimpin mereka seperti Soumokil akhirnya dihukum mati oleh pemerintah Indonesia.
Ironisnya, perlawanan RMS justru memperkuat kontrol Jakarta atas Ambon dan mempercepat integrasi Maluku ke dalam Republik Indonesia.
Setelah kejatuhan RMS, peran tentara Ambon dalam militer Indonesia juga berkurang drastis. Tidak seperti di KNIL, mereka tidak lagi menjadi kelompok yang memiliki bevoorrechte positie dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Bahkan, beberapa mantan pemimpin gerakan RMS, seperti Thomas Nussy, kemudian bergabung dengan TNI dan berperang melawan pemberontakan Darul Islam dan Permesta.
Di sisi lain, para raja juga kehilangan banyak pengaruh politik mereka. Mereka tetap dihormati dalam urusan adat, tetapi di bidang politik, mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang signifikan.
Kesimpulan
Pemberontakan RMS adalah manifestasi dari ketegangan sosial yang telah berkembang selama hampir satu abad dalam masyarakat Ambon.
Kelompok-kelompok yang mendukung RMS—tentara KNIL, raja, dan emigran Kristen—adalah mereka yang paling diuntungkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ketika kekuasaan Belanda berakhir, mereka merasa kehilangan status dan posisi mereka dalam masyarakat.
Namun, upaya mereka untuk mendirikan negara sendiri justru membawa konsekuensi yang lebih buruk bagi kelompok mereka sendiri.
Alih-alih melindungi kepentingan mereka, RMS malah mempercepat kemunduran pengaruh mereka di Ambon dan semakin memperkuat posisi pemerintah Republik Indonesia.
Dalam jangka panjang, perubahan sosial yang menyebabkan munculnya RMS juga memastikan bahwa Ambon akan tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Dokumen akademik berjudul “RMS & Social Change in Ambonese Society” yang ditulis oleh Richard Chauvel (1990), membahas perkembangan politik di Kepulauan Ambon yang mengarah pada proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS), dengan latar belakang perubahan sosial dalam masyarakat Ambon selama 90 tahun terakhir masa kolonial.