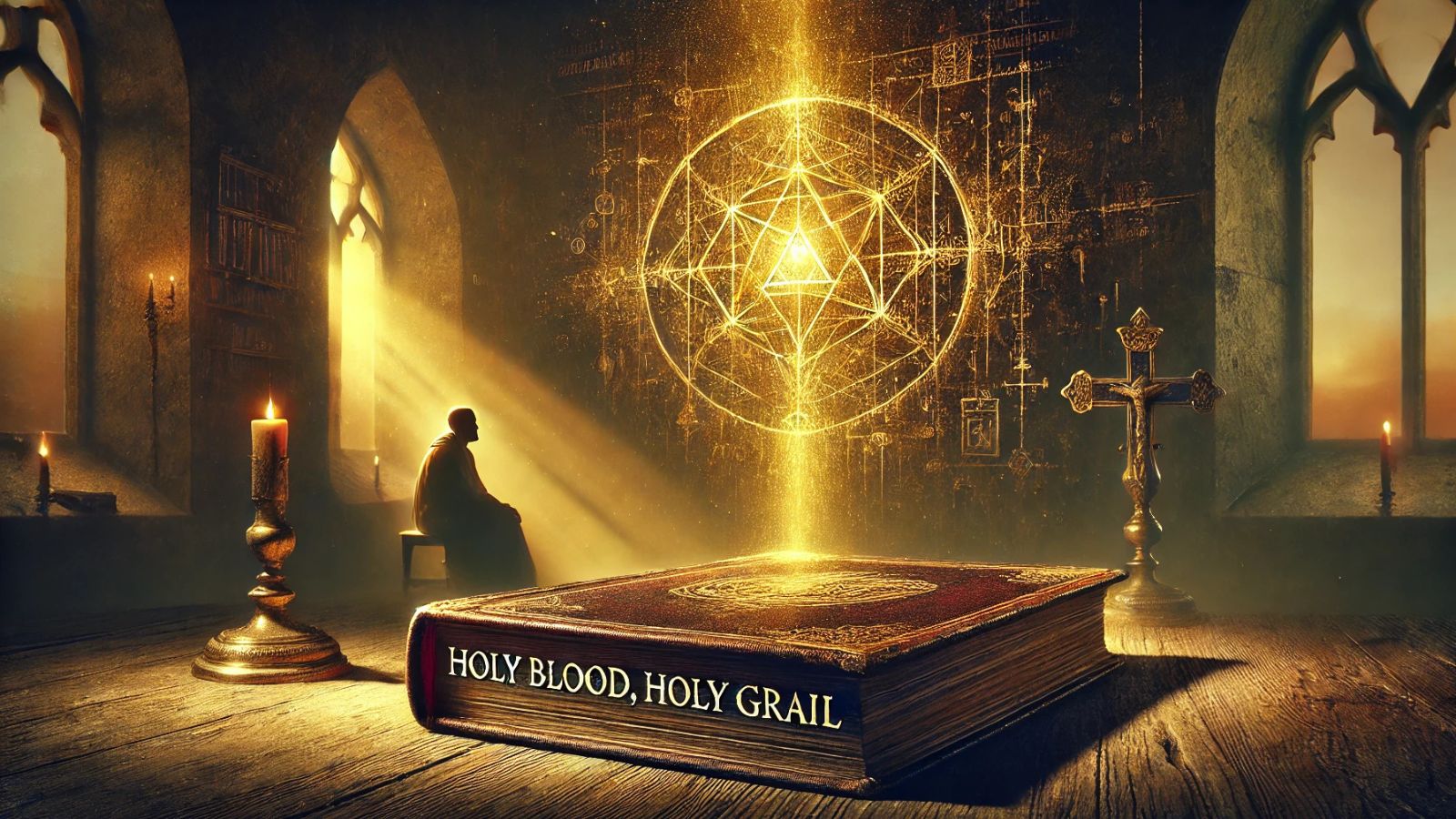Artikel ini berupaya mengkaji perkembangan politik di Kepulauan Ambon yang mengarah pada proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) dalam konteks perubahan sosial dalam masyarakat Ambon selama 90 tahun terakhir masa kolonial. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan politik ini hanya dapat dipahami dalam konteks dan struktur masyarakat di mana mereka terjadi.
Juga menyoroti berbagai kelompok dalam masyarakat Ambon, khususnya kemunculan “kelas menengah” yang terdiri dari tentara, guru, dan pejabat kecil dari komunitas Kristen, proses emansipasi dalam komunitas Muslim, serta penurunan relatif dalam kekuasaan dan otoritas para pemimpin tradisional.
Masyarakat Ambon
Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin terlebih dahulu menetapkan parameter dari “Masyarakat Ambon”. Secara geografis, masyarakat Ambon mencakup pulau-pulau Ambon, Saparua, Nusa Laut, dan Haruku, bersama dengan daerah pesisir Seram bagian selatan dan barat serta daerah pesisir Buru bagian selatan dan timur. Wilayah ini membentuk kawasan budaya Ambon yang ditandai oleh jaringan hubungan pela antar-desa (Bartels, 1977). Meskipun hubungan pela memiliki sedikit pengaruh langsung terhadap peristiwa yang dibahas dalam artikel ini, pela sebagai elemen penting dalam warisan adat yang sama melambangkan kesatuan mendasar dalam masyarakat Ambon, yang mengikat Muslim dan Kristen Ambon sebagai anggota dari satu masyarakat.
Dalam sensus terakhir pada masa kolonial, komposisi agama masyarakat Ambon adalah 65,9% Kristen dan 32,7% Muslim (Volkstelling 1930 1:91). Komunitas Kristen terbentuk akibat kontak dengan misionaris Eropa dan administrasi kolonial, sedangkan komunitas Muslim berkembang dari hubungan sebelumnya dengan para pelaut dan pedagang Muslim dari Jawa, Makassar, dan Maluku Utara. Di luar Kota Ambon, umat Kristen dan Muslim hidup di desa atau negeri yang terpisah, masing-masing dengan kepala desa atau raja sendiri. Administrasi kolonial Belanda memerintah Kepulauan Ambon melalui perantaraan para raja. Kota Ambon menjadi pusat administrasi dan perdagangan di Kepulauan Ambon serta Maluku secara keseluruhan. Dari tahun 1920-an dan seterusnya, Kota Ambon menjadi pusat aktivitas politik. Pada akhir periode kolonial, selain administrasi kolonial, masyarakat perkotaan didominasi oleh orang Ambon, meskipun ada juga penduduk Tionghoa, Arab, orang Maluku dari luar Kepulauan Ambon, dan orang Indonesia lainnya, terutama orang Buton.
Kepulauan Ambon memiliki salah satu pengalaman terpanjang dalam sejarah kolonial di Indonesia—425 tahun sejak kedatangan pedagang Portugis pertama dan hampir 300 tahun sejak Belanda berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah. Di bawah Monopoli Rempah-rempah, peran Kepulauan Ambon dalam ekonomi politik Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) adalah menghasilkan cengkeh untuk pasar dunia. Cengkeh dikirim ke VOC dengan harga tetap, terlepas dari harga pasar dunia. Sejak akhir abad ke-18, kepentingan VOC mulai bergeser ke wilayah lain di Nusantara, terutama Jawa, dan ke komoditas lain. Selama abad ke-19, Kepulauan Ambon menjadi daerah yang semakin terpinggirkan secara ekonomi, dan pada tahun 1864, monopoli cengkeh dihapuskan. Selama dekade terakhir abad ke-19, dengan pengecualian beberapa musim tertentu, masyarakat Ambon tidak lagi mendapat manfaat dari hasil panen cengkeh mereka. Upaya untuk membangun tanaman komersial alternatif gagal, dan Kepulauan Ambon ditinggalkan dengan ekonomi ekspor yang menurun serta ekonomi subsisten yang menghadapi tekanan populasi yang semakin meningkat (Chauvel, 1981).
“Kelas Menengah” Kristen
Pada dekade terakhir abad ke-19, terjadi perubahan struktural yang signifikan dalam masyarakat Ambon: kemunculan “kelas menengah” Ambon yang terdiri dari pejabat rendahan, guru, dan tentara. Berdasarkan pendidikan dan agama Kristen mereka, kelompok ini memperoleh pekerjaan di administrasi Hindia Belanda. Pada tahun-tahun terakhir periode kolonial, mereka ditemukan di seluruh kepulauan, bukan hanya di Ambon. Mereka membentuk “kelas menengah” dalam arti bahwa mereka mengembangkan jaringan hubungan baru, baik dengan masyarakat negeri Ambon maupun dengan administrasi Hindia Belanda.
Munculnya “kelas menengah” baru ini berkaitan dengan perubahan dalam ekonomi Ambon serta proses ekspansi dan konsolidasi kontrol Belanda di Nusantara. Untuk administrasi yang berkembang ini, Belanda membutuhkan tenaga kerja dan mempekerjakan ribuan orang Kristen Ambon. Sejak zaman Portugis, pendidikan telah dikaitkan dengan Kekristenan. Pada pertengahan abad ke-19, hampir setiap negeri Kristen di Kepulauan Ambon memiliki sekolah dasar. Dari tahun 1860-an, prioritas baru pemerintah Hindia Belanda menyebabkan perubahan dalam sifat sekolah negeri, dari yang awalnya sangat religius menjadi lebih sekuler dan praktis. Pada tahun 1856, sekolah “Eropa” pertama didirikan untuk orang Ambon (awalnya hanya bagi burgers), dan pada tahun 1869, sekolah ini secara resmi dikenal sebagai Ambonese Burgerschool. Pada tahun 1874, pemerintah mendirikan Ambonese Kweekschool (Sekolah Pelatihan Guru), berdasarkan kurikulum sekuler, untuk menggantikan sekolah guru misionaris. Kedua sekolah ini menandai dimulainya pendidikan dalam bahasa Belanda di Ambon.
Pendidikan bahasa Belanda diperluas hingga pada tahun 1920-an terdapat tiga sekolah dasar Eropa, tiga Hollandsch-Inlandsche Scholen, dan satu Middelbaar Uitgebreid Lager School dengan total 2.846 murid (van Sandick, 1926). Dalam masyarakat Kristen, bukan hanya anak-anak dari elit—seperti keluarga raja dan pendeta—yang memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan dalam bahasa Belanda; anak-anak berbakat dari keluarga non-elit juga memiliki kesempatan untuk meraih status sosial dan kekayaan dalam sistem kolonial yang berbasis pada pencapaian pendidikan dan pekerjaan, bukan berdasarkan ketentuan adat.
Lulusan sekolah-sekolah ini, bersama dengan tentara Ambon, menjadi simbol “orang Ambon” di mata Belanda dan orang Indonesia lainnya. Loyalitas dan identifikasi mereka dengan Belanda dianggap mewakili opini masyarakat Ambon, padahal sebenarnya kedua kelompok ini baru saja muncul dari masyarakat Kristen Ambon dan membentuk kelas sosial baru.
Tentara KNIL
Menurut tradisi militer tentara kolonial, tentara Ambon telah mengabdi kepada Belanda sejak Kapitan Jonker dan pasukannya membantu VOC mengalahkan Makassar dan Banten. Namun, perekrutan sistematis terhadap orang Ambon baru dimulai pada awal abad ke-19, ketika orang Kristen Ambon menjadi tentara yang lebih disukai. Sejak saat itu, tentara Ambon Kristen diberikan status istimewa (een bevoorrechte positie) di KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Uang pendaftaran yang diberikan kepada mereka lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan kepada tentara Jawa atau Melayu. Tentara Ambon juga menerima jatah makanan “Eropa”, serta pakaian dan akomodasi yang lebih baik.
Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Belanda adalah negara kecil di Eropa yang selama abad ke-19 berhasil memperluas administrasinya di seluruh Nusantara. Namun, mereka tidak pernah mampu merekrut cukup banyak tentara dan perwira dari Eropa untuk KNIL, karena populasi Belanda terlalu kecil dan dinas militer bukanlah profesi yang bergengsi. Akibatnya, KNIL selalu bergantung pada orang Jawa untuk mendapatkan tenaga kerja, meskipun perwira Belanda meremehkan kemampuan tempur dan mencurigai loyalitas tentara Jawa. Sementara itu, peran orang Ambon (dan Minahasa), bersama dengan orang Belanda sendiri, adalah untuk menyeimbangkan dominasi tentara Jawa. Tentara Ambon dan Minahasa dianggap lebih loyal kepada Belanda karena agama mereka, serta lebih berani dan mampu dibandingkan tentara pribumi lainnya.
Mereka diberikan status istimewa karena, hingga akhir abad ke-19, mereka selalu menjadi kelompok yang enggan direkrut. Gaji dan fasilitas yang lebih baik juga berfungsi untuk memperkuat identifikasi orang Ambon dengan kepentingan Belanda daripada dengan rekan-rekan tentara Jawa mereka. Hal ini semakin diperkuat oleh penciptaan tradisi militer Ambon yang ditekankan selama perang panjang dan berdarah di Aceh. Tradisi ini menekankan loyalitas orang Ambon kepada House of Orange (keluarga kerajaan Belanda) dan superioritas mereka atas tentara pribumi lainnya. Tentara Ambon dan Minahasa menganggap diri mereka sebagai mitra Belanda: bersama-sama mereka menegakkan rust en orde (ketertiban dan keamanan) di Hindia Belanda (lihat Dames, 1954; van Gent, 1924).
Menurut tradisi militer ini, tentara Ambon selalu setia kepada Belanda—“Ambon door de eeuwen trouw”—tetapi pada kenyataannya, orang Ambon adalah kelompok yang enggan menjadi tentara. Pada tahun 1870, ketika Belanda memulai kampanye militer di Aceh, hanya terdapat 347 tentara Ambon di KNIL, dari total sekitar 30.000 tentara (Koloniaal Verslag 1874:24). Dengan meningkatnya kebutuhan akan tentara baru, KNIL mulai membayar raja Kristen sebesar 25 gulden (kemudian meningkat menjadi 50 gulden) untuk setiap warga mereka yang direkrut. Setiap tahun, dua tentara Ambon dikirim kembali ke negeri mereka untuk membantu kampanye perekrutan.
Pada tahun 1873 dan 1875, uang pendaftaran dan pensiun bagi tentara Ambon dinaikkan lagi. Mulai tahun 1879, sekolah bahasa Belanda didirikan di kota-kota garnisun di seluruh Nusantara, khususnya untuk anak-anak tentara Ambon dan Minahasa. Namun, meskipun langkah-langkah ini diterapkan, perekrutan tentara Ambon tetap meningkat secara lambat. Belanda harus menunggu hingga tahun 1890-an sebelum jumlah rekrutmen tentara Ambon memenuhi kebutuhan mereka.
Untuk menjelaskan pola perekrutan ini, kita harus kembali ke kondisi ekonomi di Kepulauan Ambon setelah penghapusan monopoli cengkeh pada tahun 1864. Pada tahun 1870-an dan 1880-an, produsen cengkeh Ambon masih menikmati harga yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan harga monopoli sebelumnya. Namun, pada tahun 1890, harga cengkeh di pasar dunia anjlok dan tetap rendah hingga setelah kemerdekaan Indonesia (Koloniaal Verslag 1861-1900). Dengan kata lain, selama dekade terakhir abad ke-19, terutama setelah tahun 1890, perbedaan standar hidup dan peluang mobilitas sosial antara masyarakat negeri di Ambon dan apa yang ditawarkan oleh KNIL meningkat secara signifikan.
Pada abad ke-19, orang Ambon enggan menjadi tentara; tetapi pada abad ke-20, mereka mulai bergantung pada KNIL untuk mencapai kemajuan ekonomi. Loyalitas kepada House of Orange, seperti yang dirayakan dalam tradisi militer, pada kenyataannya adalah ketergantungan ekonomi.
Kepulauan Ambon menjadi daerah yang semakin terpinggirkan secara ekonomi. Pendidikan Barat, khususnya sekolah bahasa Belanda, menjadi jalan keluar bagi kaum muda yang ambisius. Mereka yang mampu lulus kleinambtenaars examen (ujian pegawai rendah) dapat menjadi pejabat dalam administrasi kolonial yang berkembang. Sementara itu, mereka yang tidak mampu, tetapi cukup kuat secara fisik, bisa bergabung dengan KNIL.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ribuan orang Kristen meninggalkan Ambon untuk bekerja di administrasi Hindia Belanda. Pada tahun 1930, setidaknya 16 persen dari komunitas Kristen Ambon tinggal dan bekerja di luar Maluku (Volkstelling 1930 5:24, tabel 2, 4-1; 1:38; 3:212). “Kelas menengah” Kristen ini menjadi, dalam beberapa hal, terasing dari masyarakat Kepulauan Ambon karena, secara fisik, mereka menghabiskan sebagian besar masa kerja mereka di tempat lain di Nusantara. Selain itu, status yang mereka peroleh dari kolonialisme—bevoorrechte positie tentara—hanya sebagian diakui dalam masyarakat negeri, yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem status adat.
Sering kali, tentara dan pejabat yang kembali ke Ambon dengan pensiun dan ambisi untuk menjadi pemimpin merasa frustrasi dan kecewa. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa pengalaman dan status mereka di luar negeri tidak diakui atau dihargai di kampung halaman mereka.
Emansipasi Komunitas Muslim
Masyarakat Muslim Ambon tidak berpartisipasi dalam proyek kolonial akhir seperti halnya komunitas Kristen. Mereka tidak direkrut ke dalam KNIL karena mereka tidak dapat memenuhi fungsi yang diinginkan dari seorang tentara “Ambon”, yaitu tentara Kristen yang berperan sebagai penyeimbang terhadap rekan-rekan Muslim mereka dari wilayah lain di Nusantara. Raja dari negeri-negeri Muslim tidak dibayar untuk setiap warganya yang direkrut. Jika seorang Muslim Ambon bergabung dengan KNIL, ia menerima gaji dan kondisi kerja yang sama seperti tentara Jawa, bukan seperti sesama orang Ambon Kristen. Baru pada menjelang Perang Dunia II, Belanda mulai merekrut Muslim Ambon untuk kontrak jangka pendek.
Di Kepulauan Ambon, pendidikan Barat telah dikaitkan dengan Kekristenan. Sekolah dasar pertama untuk negeri-negeri Muslim baru didirikan pada tahun 1920-an di enam negeri Muslim. Namun, sekolah-sekolah ini hanya menawarkan pendidikan selama tiga tahun dibandingkan dengan lima tahun di sekolah negeri Kristen. Selain itu, sekolah-sekolah Muslim menerima subsidi pemerintah yang lebih kecil, dan guru-guru mereka kurang terlatih dibandingkan dengan guru di negeri Kristen (Schmidt, 1924). Partisipasi Muslim dalam pendidikan bahasa Belanda sangat terbatas. Pada tahun 1926, kurang dari 5% siswa sekolah berbahasa Belanda adalah Muslim, dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak raja atau Muslim non-Ambon yang tinggal di Kota Ambon (van Sandick, 1926, vol. 5, lampiran 11).
Namun, situasi ini bukan hanya akibat kebijakan kolonial. Masyarakat Muslim sendiri sering menganggap bahwa masuk KNIL atau menghadiri sekolah pemerintah adalah tindakan yang mendekati perpindahan agama ke Kristen (Tausikal, 1951:387).
Meskipun Muslim Ambon tidak berpartisipasi dalam proyek kolonial, mereka tetap terpengaruh oleh perubahan dalam sistem kolonial sejak akhir abad ke-19. Penghapusan monopoli cengkeh dan perbaikan transportasi memfasilitasi kebangkitan kembali hubungan antara komunitas Muslim Ambon dan pusat-pusat Islam di Nusantara serta di luar negeri. Sebagai contoh, pada tahun 1870, hanya ada 36 orang Muslim Ambon yang telah menunaikan haji di seluruh Residensi Amboina. Namun, dalam beberapa dekade berikutnya, jumlah jamaah haji meningkat dari puluhan menjadi ratusan setiap tahunnya pada tahun 1920-an (Politiek Verslag Residentie Amboina 1870; Koloniaal Verslag, 1871–1898; van Sandick, 1926).
Perjalanan haji tidak hanya membawa pengalaman keagamaan, tetapi juga memperkenalkan gagasan-gagasan baru serta kesadaran bahwa praktik Islam di luar Ambon sering kali berbeda dengan praktik di kalangan Muslim Ambon. Haji memainkan peran penting dalam proses pembaruan di negeri-negeri Muslim. Selain itu, banyak Muslim Ambon yang menjadi pelaut dan pedagang keliling, dan pengalaman mereka di dunia luar memperkuat identitas mereka sebagai Muslim serta keterhubungan mereka dengan sesama Muslim di Nusantara.
Sebaliknya, pengalaman orang Ambon Kristen sebagai pegawai pemerintah kolonial justru membuat mereka semakin membedakan diri dari orang Indonesia lainnya. Para emigran Kristen mengembangkan rasa superioritas terhadap orang Indonesia lainnya dan lebih mengidentifikasi diri mereka dengan kepentingan Belanda.
Dengan munculnya gerakan nasionalis Indonesia, orang Ambon Kristen—terutama mereka yang tinggal di luar Ambon—menghadapi dilema. Mereka adalah di antara kelompok pertama di Indonesia yang merasakan manfaat pendidikan Barat dan peluang mobilitas sosial yang diberikannya. Mereka dengan cepat menyadari bahwa peluang lebih besar dapat diperoleh melalui pembentukan organisasi sosial, dan kemudian organisasi politik, mereka sendiri.
Hanya setahun setelah Boedi Oetomo berdiri, orang Ambon Kristen mendirikan Ambonsch Studiefonds, sebuah organisasi yang memberikan beasiswa bagi anak-anak Kristen yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan. Organisasi ini dipimpin oleh emigran Kristen, sebagian besar dari mereka adalah pejabat pemerintah, sementara mayoritas anggotanya adalah tentara KNIL (Manusama, 1919).
Namun, mereka menghadapi pertanyaan besar: sejauh mana mereka dapat memperoleh emansipasi dan kemajuan dengan tetap bekerja dalam sistem kolonial? Apakah mereka akan puas dengan bevoorrechte positie mereka—yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Indonesia lainnya, tetapi tetap tidak setara dengan orang Belanda? Ataukah mereka akan bergabung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun berisiko menjadi minoritas kecil dalam negara baru?
Dilema ini menghasilkan dua orientasi dalam organisasi sosial dan politik Ambon sebelum Perang Pasifik: mereka yang ingin mencapai emansipasi dalam sistem kolonial, dan mereka yang menyadari bahwa kemajuan dalam sistem kolonial akan selalu dibatasi—dan bahwa emansipasi sejati hanya mungkin terjadi dalam Indonesia yang merdeka.
Sementara itu, komunitas Muslim Ambon tidak mengalami dilema ini. Dalam komunitas Muslim, hanya raja yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo kolonial. Mereka merasa bergantung pada administrasi kolonial Hindia Belanda untuk status dan kekuasaan mereka. Namun, sejak tahun 1917, cabang Insulinde (organisasi politik awal yang mengadvokasi otonomi Indonesia dalam sistem kolonial Belanda) telah didirikan di Ambon, dan pada tahun 1923 organisasi ini digantikan oleh Sarekat Ambon, yang juga dipimpin oleh orang Kristen yang berpendidikan Belanda, tetapi memiliki banyak anggota dari komunitas Muslim.
Penurunan Kekuasaan Tradisional
Raja dalam setiap negeri adalah kunci utama dalam sistem pemerintahan kolonial di Kepulauan Ambon. Mereka adalah perantara antara otoritas Hindia Belanda dan masyarakat negeri. Para raja memiliki tiga fungsi utama yang sering kali saling bertentangan:
- Sebagai pemimpin negeri: Mereka dianggap sebagai pelindung rakyat mereka dan perwakilan mereka dalam dunia luar.
- Sebagai perwakilan otoritas tertinggi Belanda: Mereka secara resmi diangkat oleh penguasa kolonial.
- Sebagai agen negara kolonial: Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, mengorganisir kerja paksa, dan menjaga ketertiban umum.
Kekuasaan seorang raja dalam masyarakat adat didasarkan pada warisan dalam mata rumah (klan patrilineal). Kemakmuran dan harmoni negeri diyakini bergantung pada memiliki raja yang “benar”. Pihak kolonial mengakui ideal legitimasi ini dan berusaha menerapkannya, tetapi dalam praktiknya hal ini sering kali sulit. Beberapa negeri memiliki lebih dari satu mata rumah yang berhak atas posisi raja, yang sering kali memicu konflik internal yang berkelanjutan.
Pada tahun 1824, Molukken Publicatie (peraturan kolonial tentang administrasi di Maluku) mengkritik orang Ambon karena:
“Kalian membenci dan tidak menghargai otoritas sah para pemimpin, yang berasal dari keluarga-keluarga lama kalian, karena kepentingan mereka tidak sama dengan kepentingan kalian” (Gouvernements Gazette, 1824, no. 19a).
Meskipun raja mempertahankan status mereka hingga Perang Dunia II, proses penurunan kekuasaan mereka sudah dimulai sejak abad ke-19.
Pendudukan Jepang dan Revolusi
Pada tanggal 31 Januari 1942, dalam waktu 24 jam, Jepang mengakhiri 286 tahun kekuasaan Belanda di Kepulauan Ambon. Selama tiga setengah tahun berikutnya, kebijakan dan praktik administrasi Jepang mempercepat proses perubahan sosial dan politik yang telah berkembang sebelumnya. Hal ini terutama terlihat dalam bidang administrasi pemerintahan serta hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen di Ambon.
Jepang menggantikan pejabat-pejabat dari keluarga raja yang paling bergengsi di Ambon dengan politisi nasionalis. E. U. Pupella, pemimpin Sarekat Ambon, diangkat sebagai Bunkencho (Kepala Subresidensi Pulau Ambon), dan rekan-rekannya diberikan posisi senior dalam administrasi lokal. Simbol dari perubahan ini adalah bahwa salah satu tugas Pupella adalah mengawasi pemilihan raja di negeri-negeri, padahal sebelum perang, ia bahkan tidak diperbolehkan masuk ke dalam negeri-negeri tersebut.
Organisasi pemuda seperti Seinendan dan Ambon Hookoo Kai dimobilisasi di bawah kepemimpinan nasionalis. Surat kabar Jepang, Sinar Matahari, memiliki editor nasionalis.
Kehadiran Jepang juga mengubah keseimbangan dalam masyarakat Ambon. Berlawanan dengan praktik kolonial Belanda yang mendukung elit adat dan komunitas Kristen, Jepang lebih mendukung kaum nasionalis serta lebih memperhatikan komunitas Muslim.
Pada awal pendudukan, Gereja Protestan Maluku kehilangan perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam beberapa bulan pertama, gereja mengalami penindasan yang cukup berat, dan beberapa pendeta terbunuh. Pada saat yang sama, Jepang mendirikan organisasi Islam bernama Djamijah Islamijah Ceram untuk memperkuat pembaruan dan persatuan dalam komunitas Muslim. Organisasi Kristen yang didukung Jepang baru didirikan kemudian.
Jepang berhasil menggeser keseimbangan masyarakat Ambon. Mereka mendukung nasionalis daripada elite adat dan lebih memperhatikan komunitas Muslim daripada komunitas Kristen (lihat Chauvel, 1985).
Pada bulan September 1945, pejabat Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dengan bantuan tentara Australia berhasil memulihkan pemerintahan Belanda di Ambon. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan isolasi politik pra-perang maupun membalikkan proses perubahan sosial yang telah terjadi.
Di bawah negara boneka Belanda, Negara Indonesia Timur (NIT), Ambon menjadi ibu kota Daerah Maluku Selatan dengan lembaga demokrasi yang masih berkembang. Pada tahun 1946 dan 1948, pemilihan umum diadakan untuk Dewan Maluku Selatan (DMS). Dalam kedua pemilihan ini, Partai Indonesia Merdeka (PIM), yang dipimpin oleh E. U. Pupella, muncul sebagai partai yang paling kuat dan terorganisir dengan baik.
Seperti halnya organisasi nasionalis sebelum perang, PIM adalah sebuah koalisi, di mana sebagian besar pemimpinnya adalah Kristen, sementara basis keanggotaannya sebagian besar adalah Muslim. Ironisnya, ketika Belanda meresmikan Door de Eeuwen Trouw (Monumen Kesetiaan) di Ambon untuk memperingati loyalitas orang Ambon terhadap Belanda, mayoritas anggota Dewan Maluku Selatan yang didukung oleh Belanda sudah tidak lagi mendukung nilai-nilai tersebut atau interpretasi sejarah kolonial yang mereka representasikan.