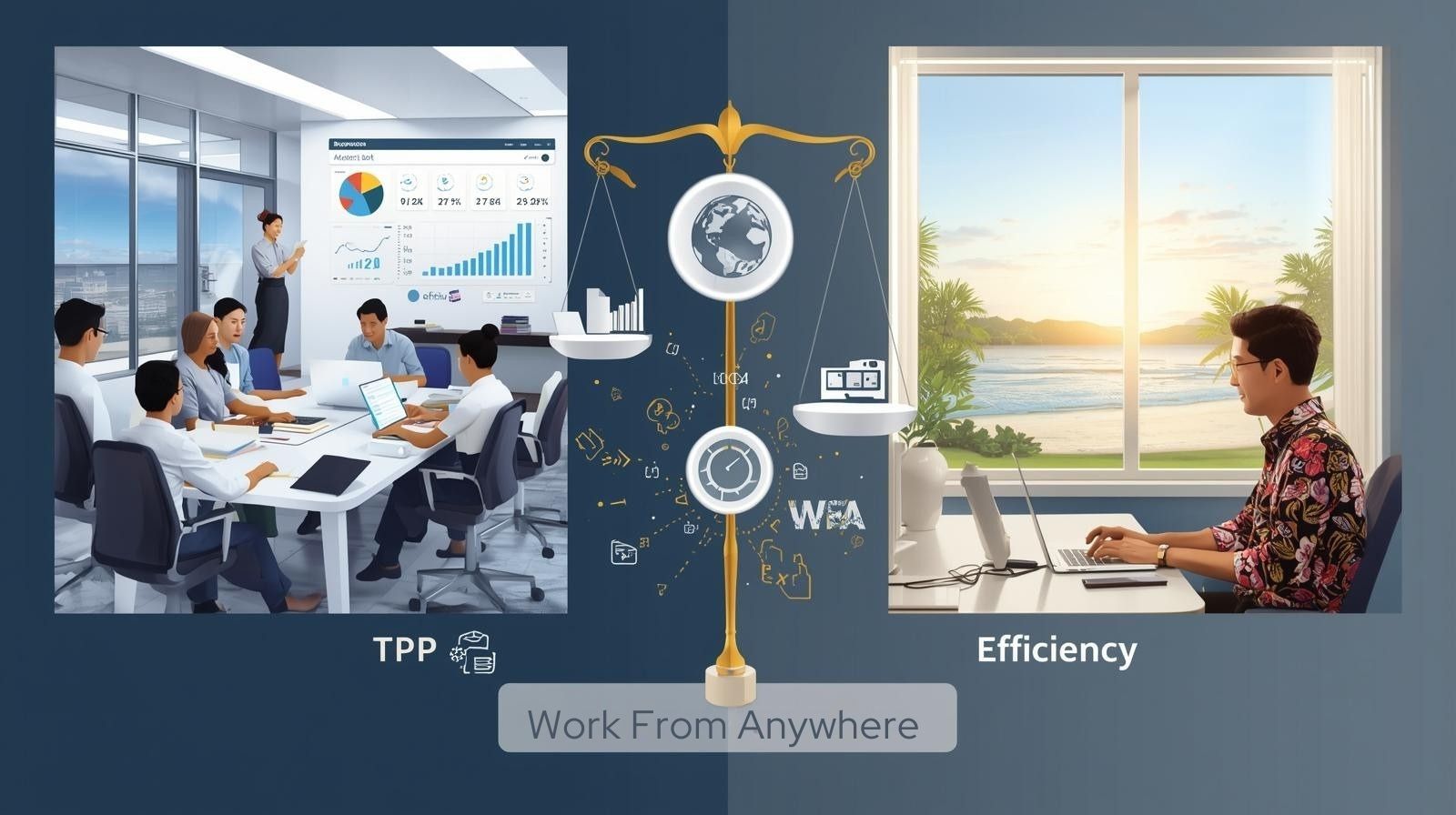Di sudut Jakarta yang padat dan penuh tekanan, utang bukan sekadar angka dalam buku catatan—ia adalah bom waktu sosial yang bisa meledak kapan saja. Praktik penagihan utang oleh para “mata elang” sering kali berjalan di garis tipis antara penegakan kontrak dan pelanggaran kemanusiaan. Ketika metode intimidasi, penyitaan paksa, dan teror psikologis menjadi hal biasa, masyarakat pun terbelah: antara rasa takut pada utang dan kemarahan pada cara menagihnya. Insiden pengeroyokan dua debt collector di Kalibata pada Desember 2025 bukanlah insiden terisolasi, melainkan puncak dari krisis sosial yang telah lama mengendap—krisis yang melibatkan ketimpangan ekonomi, regulasi yang bolong, dan kekerasan yang dibenarkan atas nama “profesi”.
Insiden pengeroyokan dua orang yang bekerja sebagai penagih utang hingga tewas di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 Desember 2025, merupakan titik ekstrem dari ketegangan yang telah membangun selama bertahun-tahun antara para penagih utang, masyarakat sipil, dan bahkan aparat negara. Insiden ini bukanlah sebuah kejadian isolatif, melainkan sebuah cerminan dramatis dari kompleksitas ekosistem penagihan utang yang sarat dengan risiko sosial dan kekerasan di ibu kota. Untuk memahami dampaknya yang luas, penting untuk merekonstruksi kronologi kejadian secara cermat, mengidentifikasi peran pelaku dan korban, serta menganalisis dampak ganda yang ditimbulkannya baik pada level individu maupun komunitas.
Kronologi dan Dampak Insiden Pengeroyokan Mata Elang di Kalibata
Insiden bermula pada pukul 15.45 WIB saat petugas Polsek Pancoran menerima laporan mengenai adanya penganiayaan di area parkir dekat TMP Kalibata. Aksi kekerasan ini dipicu oleh sebuah konfrontasi yang tampaknya bersifat personal namun memiliki akar yang lebih dalam terkait metode penagihan paksa. Menurut penyampaian Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu, 13 Desember 2025, salah satu dari dua korban, yaitu seorang oknum anggota Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri berinisial Brigadir AM, menghentikan secara paksa sepeda motor milik korban MET (41 tahun). Aksi tersebut dilanjutkan dengan pencabutan kunci kontak kendaraan oleh korban MET. Langkah ini, yang merupakan tindakan penarikan paksa kendaraan di jalan raya, merupakan pelanggaran prosedur yang dibenarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan kendaraan. Praktik ilegal semacam ini kerap terjadi karena penugasan sering kali tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) yang jelas dan dilakukan oleh petugas yang kurang pemahaman hukum atau pelatihan yang memadai.
Konfrontasi awal ini kemudian memicu intervensi lima rekannya sesama anggota Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri, yaitu Brigadir IAM, Brigadir JLA, Brigadir RGW, Brigadir IAB, dan Brigadir BN. Dengan demikian, total enam anggota polisi aktif turut serta dalam aksi pengeroyokan terhadap kedua korban. Keanehan dan keparahan insiden ini terletak pada fakta bahwa pelaku utama adalah aparat negara—lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Peran institusi ini dalam memicu dan melaksanakan kekerasan fisik menunjukkan adanya fenomena yang bisa disebut regresi hukum, di mana norma-norma dan prosedur yang benar digantikan oleh logika kekuasaan dan kekerasan fisik. Fenomena ini diperparah oleh status mereka sebagai anggota polisi, yang secara inheren memiliki otoritas dan kekuatan yang dapat ditiru atau ditantang oleh massa, menciptakan potensi eskalasi konflik yang tinggi.
Korban dari pengeroyokan tersebut adalah MET berusia 41 tahun dengan domisili di Jakarta Pusat, dan NAT berusia 32 tahun dengan domisili di Kota Bekasi. Visum luar yang dilakukan menyimpulkan bahwa kedua korban meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita karena pukulan benda tumpul, dengan luka yang berasal dari kekerasan fisik menggunakan tangan kosong, tanpa ditemukan adanya luka akibat senjata tajam. Korban MET meninggal dunia di lokasi kejadian sekitar pukul 16.00 WIB, sementara korban NAT sempat dilarikan ke Rumah Sakit Budhi Asih namun juga meninggal dunia pada hari berikutnya, Jumat, 12 Desember 2025. Polda Metro Jaya telah menetapkan keenam anggota polisi tersebut sebagai tersangka dengan dakwaan Pasal 170 ayat (3) KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Proses hukum pun berjalan cepat; dalam waktu kurang dari 24 jam sejak kejadian, keenam oknum tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain proses pidana, mereka juga menjalani proses etik oleh Divisi Propam Polri, dengan sidang Komisi Kode Etik Polri dijadwalkan pada Rabu, 17 Desember 2025.
Setelah kedua korban tewas, insiden ini tidak berhenti di situ. Sebuah kelompok massa yang diduga merupakan rekan-rekan korban ‘mata elang’ melakukan tindakan pembalasan yang terorganisir dan sistematis. Mereka secara sengaja menghancurkan fasilitas milik warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Tindakan pembalasan ini termasuk perusakan dan pembakaran terhadap puluhan kios, lapak pedagang, dan kendaraan bermotor. Polisi menduga bahan bakar yang digunakan untuk pembakaran adalah bensin. Aksi ini terjadi setelah maghrib pada malam yang sama, menunjukkan niat yang telah direncanakan (“sudah berencana mau membalas”). Tindakan ini memicu kebakaran besar-besaran di Jalan H Mahmud Raya, Blok Langgar Nomor 1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, pada pukul 23.35 WIB. Api berhasil dipadamkan oleh tim Gulkarmat DKI Jakarta pada pukul 01:02 WIB pada tanggal 12 Desember 2025, setelah mobilisasi 49 personel dan 6 unit pompa.
Dampak dari insiden ini sangatlah signifikan dan multifaset, meliputi kerugian jiwa, kerusakan materiil yang masif, dan trauma psikologis bagi masyarakat sekitar. Secara materiil, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Estimasi kerugian materiil akibat kericuhan di depan TMP Kalibata pada 11 Desember 2025 mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Kerugian ini meliputi kerusakan dan pembakaran terhadap sembilan sepeda motor, satu unit mobil, sejumlah warung tenda milik warga, serta kerusakan pada kaca dan bangunan rumah warga. Data lain yang dikutip oleh Polda Metro Jaya menyebutkan kerusakan pada 4 unit kendaraan roda empat, 7 unit sepeda motor, 14 lapak pedagang, 2 kios terbakar/rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan (kaca pecah). Total kerugian materiil yang ditaksir oleh Sudin Gulkarmat DKI Jakarta sendiri adalah Rp273 juta, yang meliputi 9 kios, 8 kendaraan (6 sepeda motor dan 1 mobil), serta 14 lapak pedagang.
Namun, dampak yang paling serius dari kerusakan materiil ini adalah dampak ekonomi dan sosialnya bagi komunitas lokal. Banyak dari kios dan warung tenda yang terbakar merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, insiden ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial langsung tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan ketahanan hidup komunitas di sekitar lokasi kejadian. Korban-korban perusakan dan pembakaran tersebut bahkan enggan melapor ke polisi karena trauma psikologis yang mendalam pasca-kejadian. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kerugian aktual yang dialami oleh masyarakat dan data resmi yang tercatat, sehingga upaya rehabilitasi dan pemulihan dapat tertunda. Polisi masih harus menunggu laporan resmi dari korban sebelum dapat memproses hukum para pelaku perusakan dan pembakaran.
Keluarga korban juga mengalami dampak psikologis yang mendalam. Salah satunya, keluarga korban MET, menolak untuk melakukan autopsi atas jenazahnya, sebuah tindakan yang jarang terjadi dan menunjukkan tingkat keputusasaan dan kegagapan hukum yang dialami keluarga tersebut. Polda Metro Jaya sendiri mengakui belum dapat memverifikasi status tunggakan kendaraan dari korban, termasuk atas nama siapa utang tersebut, berapa lama kredit sudah berjalan, dan berapa nilai tunggakannya, yang menambah lapisan misteri pada latar belakang insiden ini. Meskipun penyidik juga mendalami keberadaan mata elang lain di lokasi yang diduga melarikan diri, fokus utama investigasi tetap pada peran keenam oknum anggota polisi tersebut.
Secara keseluruhan, insiden Kalibata berfungsi sebagai studi kasus yang kuat tentang bagaimana sengketa kecil yang bersumber dari praktik penagihan utang yang tidak manusiawi dapat berevolusi menjadi bencana sosial dan ekonomi yang parah. Titik temu antara regresi hukum yang dilakukan oleh aparat negara, kekerasan balasan oleh kelompok massa, dan kerusakan materiil yang masif menciptakan situasi zero-sum di mana semua pihak—korban, pelaku, dan masyarakat sipil—merugi. Insiden ini menyoroti urgensi untuk memahami konteks sosial yang lebih luas di mana praktik penagihan utang ini beroperasi, serta celah-celah regulasi yang memungkinkan perilaku buruk ini terus terjadi.
Konteks Sosial Utang Konsumtif dan Kerentanan Masyarakat
Untuk sepenuhnya memahami mengapa insiden pengeroyokan di Kalibata bisa terjadi, serta mengapa ia memicu respons kekerasan yang begitu ekstrem, kita harus menyelami konteks sosial yang lebih luas di mana praktik penagihan utang ini beroperasi. Insiden tersebut bukanlah sebuah anomali, melainkan sebuah manifestasi dari serangkaian masalah struktural yang lebih dalam, terutama terkait dengan maraknya utang konsumtif dan kerentanan ekonomi yang meluas di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Fenomena “kelas menengah aspiratif”—sebuah segmen populasi yang berada di antara golongan miskin dan mapan—menjadi korban paling rentan dalam dinamika ini.
Kelas menengah aspiratif ini sering kali berada dalam posisi ekonomi yang rapuh. Antara tahun 2019 dan 2024, sebanyak 80% dari semua pekerjaan baru di Indonesia berasal dari sektor informal. Pendapatan rata-rata pekerja di sektor formal pada tahun 2023 adalah Rp2,9 juta ($181 USD), sementara pendapatan rata-rata pekerja di sektor informal jauh lebih rendah, yaitu Rp1,9 juta ($114 USD) per bulan. Ketidakpastian pekerjaan, gaji yang rendah, dan minimnya jaminan sosial membuat mereka sangat mudah terjerat dalam sumber utang konsumtif, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal atau fasilitas Paylater. Tekanan untuk mempertahankan status sosial dan gaya hidup yang dianggap layak juga menjadi pendorong utama. Akibatnya, banyak dari mereka yang meminjam uang untuk tujuan non-esensial, seperti membeli ponsel pintar atau barang elektronik lainnya, tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar mereka secara realistis.
Sebuah studi kasus yang dilaporkan LBH Jakarta memberikan gambaran nyata tentang dampak psikologis dan sosial dari utang konsumtif ini. NP, seorang mahasiswi berusia 21 tahun dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, mengambil pinjaman untuk membeli sebuah ponsel pintar yang nilainya mencapai hampir lima kali lipat dari penghasilan bulanan yang ia dapatkan, yang berkisar antara $95 hingga $300. Akibatnya, ia kini menerima lebih dari 20 panggilan telepon dari penagih utang setiap harinya, merasakan teror yang mendalam, dan bahkan menyembunyikan utangnya dari orang tua untuk tidak membebani mereka. Kisah ini menggambarkan bagaimana utang konsumtif dapat menyebabkan stres mental yang parah dan isolasi sosial yang dipicu oleh rasa malu.
Kasus lain yang lebih parah datang dari M, seorang wanita berusia 30 tahun dari Subang, Jawa Barat. Ia menggunakan aplikasi SPaylater untuk berdagang, namun kemudian terperosok ke dalam utang yang melebihi Rp30 juta setelah uang cicilan tersebut dialihkan untuk membayar biaya medis keluarganya. Upah bulanan suaminya yang hanya sebesar Rp 3 juta terbukti tidak cukup untuk melunasi utang tersebut, yang kemudian mendorongnya untuk mengunduh beberapa aplikasi pinjaman online lainnya demi menutupi utang sebelumnya. Ini adalah contoh klasik dari “perangkap utang” (debt trap), di mana utang baru digunakan untuk membayar utang lama, menciptakan siklus yang sulit untuk dihentikan. Kurangnya literasi finansial dan ketiadaan program restrukturisasi utang yang mudah diakses bagi masyarakat menengah membuat mereka rentan terhadap skenario ini.
Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang rapuh ini, industri fintech dan pinjol ilegal tumbuh subur, menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang sangat longgar, sering kali tanpa verifikasi pendapatan yang memadai. Namun, di balik layar, kondisi ini menunjukkan adanya regresi sosial yang signifikan. Teori konflik sosial, misalnya, menjelaskan bagaimana insiden Kalibata dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan dari individu atau kelompok yang merasa tertindas oleh kekuatan elite, seperti kreditor, bank, atau pemerintah. Di Jakarta, sebuah kota dengan urbanisasi tinggi, tingkat kemiskinan relatif tinggi, dan mobilitas sosial yang rendah, ketidaksetaraan antara kelas atas dan bawah menjadi sangat jelas. Kelas menengah yang rentan ini, yang merasa tertekan oleh sistem, cenderung melihat debt collector sebagai agen dari sistem tersebut dan melakukan kekerasan sebagai bentuk resistensi atau perlawanan.
Selain itu, kondisi proteksi sosial yang lemah juga memperburuk situasi. Anggaran perlindungan sosial di Indonesia mengalami penurunan setelah periode lonjakan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dan hanya sedikit ditingkatkan kembali menjelang pemilihan umum pada tahun 2024 sebelum kembali menurun. Aspirational middle class di Indonesia sering kali dilewati oleh program-program bantuan sosial seperti transfer tunai, beasiswa, dan asuransi kesehatan subsidi, meninggalkan mereka dalam kondisi kronis rentan terhadap goncangan ekonomi. Hal ini menciptakan lapisan masyarakat yang tidak miskin menurut ukuran resmi, tetapi juga tidak aman secara finansial, yang membuat mereka mudah sekali terjerat dalam utang konsumtif. Regresi ini diperkuat oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, diversitas etnis, ketidakstabilan perumahan, dan kurangnya jaringan sosial yang kuat di permukiman kumuh, yang semuanya mempersulit kapasitas lingkungan untuk mengatur perilaku publik dan meningkatkan kerentanan terhadap aktivitas kriminal dan kontrol mafia lokal.
Akibat dari semua faktor ini, banyak dari masyarakat yang terjerat utang konsumtif mengalami degradasi finansial yang signifikan. Pertumbuhan tabungan di bawah Rp100 juta melambat dari sekitar 8% menjadi di bawah 5%, sementara saldo rata-rata deposito turun sebesar 40%. Indikator-indikator ekonomi makro lainnya juga menunjukkan adanya penurunan daya beli. Misalnya, penjualan produk Unilever Indonesia pada tahun 2023 berada di bawah tingkat penjualan pada tahun 2016. Tingkat kemiskinan relatif juga meningkat, dengan 23,0% penduduk perkotaan di Jakarta tinggal di permukiman kumuh pada tahun 2010, yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas hidup di tengah pertumbuhan ekonomi nasional. Semua ini menunjukkan bahwa utang konsumtif bukan lagi hanya masalah individual, melainkan sebuah gejala dari masalah struktural yang lebih besar dalam distribusi kekayaan dan aksesibilitas perlindungan sosial di Indonesia.
Dalam konteks inilah, debt collector sering kali menjadi simbol dari tekanan ekonomi yang tak terhindarkan dan sering kali dianggap tidak manusiawi. Mereka adalah “wajah” dari sistem finansial yang membebani mereka, sehingga memunculkan persepsi bahwa mereka adalah musuh yang sah untuk dilawan, terutama ketika metode penagihan mereka dianggap melanggar batas-batas etika dan hukum. Ketika interaksi fisik terjadi, seperti dalam kasus Kalibata, percikan api yang memicu kerusuhan massal ini sering kali menjadi hasil dari ketegangan yang telah membangun selama bertahun-tahun antara debitur yang putus asa dan kreditor yang tidak sabar.
Metodologi Intimidasi dan Penghancuran Hubungan Sosial oleh Penagih Utang
Praktik penagihan utang di Jakarta tidak hanya dibentuk oleh tekanan ekonomi yang dirasakan oleh debitur, tetapi juga oleh metodologi penagihan yang sering kali dirancang secara sadar untuk menekan secara intensif dan merusak hubungan sosial korban. Metode-metode ini, yang sering kali melanggar aturan hukum yang ada, tidak hanya bertujuan untuk memaksa pembayaran, tetapi juga secara efektif memecah jaringan dukungan sosial korban, membuat mereka merasa terisolasi dan tidak punya tempat untuk berlindung. Dengan demikian, metode-metode ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan dan konflik lebih mungkin untuk terjadi. Beberapa teknik yang paling umum digunakan meliputi intimidasi publik, pelanggaran privasi yang ekstrem, dan ancaman terhadap identitas serta harta benda.
Salah satu bentuk intimidasi yang paling umum adalah public shaming atau penghinaan publik. MSS, seorang debt collector berpengalaman dari Jakarta dengan sekitar 30 operatif di bawahnya, secara eksplisit mengakui penggunaan teknik-teknik ini dalam bisnisnya. Dia menjelaskan penggunaan pengumuman publik di depan rumah korban menggunakan pengeras suara, penempelan spanduk atau poster di pagar depan yang berisi nama korban dan jumlah utang yang mereka tanggung, serta intimidasi melalui penyewaan orang-orang yang diasosiasikan dengan kekuatan fisik, seperti spiritual advisor atau bahkan janji untuk mengunjungi penjara. Teknik-teknik ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki “rasa malu” universal, dan dengan mengeksploitasi rasa malu ini, para penagih dapat menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar. Bahkan, ia mengklaim bahwa metode-metode ini telah divalidasi oleh petugas hukum, menunjukkan adanya kolusi atau toleransi dalam implementasinya.
Metode lain yang sering digunakan adalah ancaman verbal dan fisik, serta penyitaan paksa aset. Dalam kasus L., seorang wanita berusia 40 tahun dari Central Jakarta, dia menerima panggilan dan pesan teks yang mengancam setiap hari setelah gagal membayar pinjaman Rp 500.000 dari sebuah aplikasi berbasis smartphone. Ancaman-ancaman ini tidak hanya ditujukan padanya, tetapi juga kepada suaminya, menciptakan atmosfer teror yang meresap ke dalam kehidupan pribadi mereka. Akibatnya, L. mengalami depresi parah hingga berujung pada upaya bunuh diri. Demikian pula, kasus SN, seorang wanita berusia 30 tahun, mengalami pelecehan setelah kolektor utang palsu menyatakan bahwa atasannya adalah penjamin utangnya dan kemudian menghubungi tempat kerjanya tanpa izin, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja dan depresi berat. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana ancaman terhadap identitas profesional dan sosial seseorang dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memaksa pembayaran.
Namun, metode yang paling merusak dan secara sistematis menghancurkan jaringan sosial debitur adalah pelanggaran privasi yang ekstrem. Salah satu pelanggaran paling sering dilaporkan adalah akses tak sah ke daftar kontak pribadi (kontak telepon, WhatsApp, media sosial) yang ada di ponsel debitur. Para penagih utang menggunakan daftar ini untuk menghubungi teman, keluarga, tetangga, dan rekan kerja korban, meminta mereka untuk memberi tekanan agar korban segera membayar utangnya. Menurut laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, banyak korban melaporkan bahwa kerabat dan rekan kerja mereka dieksploitasi untuk tujuan penagihan meskipun mereka tidak pernah memberikan izin untuk berbagi informasi kontak tersebut. Praktik ini bukan hanya melanggar hak privasi, tetapi juga secara efektif menciptakan lingkungan di mana debitur tidak lagi dapat mempercayai siapa pun, termasuk orang-orang terdekat mereka.
Penting untuk dicatat bahwa banyak dari praktik-praktik ini, terutama yang dilakukan oleh “Pinjol ilegal”, merupakan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 (pasal 7) secara eksplisit memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mencegah direktur, karyawan, atau pihak ketiga (termasuk debt collector) dari melakukan tindakan yang merugikan konsumen, yang secara spesifik menyebutkan “melakukan kekerasan saat menagih utang” sebagai tindakan yang dilarang. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan OJK 35/POJK.05.05/2018 (pasal 47–48) dan Peraturan Bank Indonesia 22/20/PBI/2020 (pasal 40), yang semuanya menegaskan bahwa penagihan harus dilakukan secara etis, non-komersial, dan tanpa kekerasan atau ancaman . Lebih lanjut, Peraturan OJK 22/2023 secara tegas melarang debt collector dari menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan fisik/verbal, penghinaan publik, atau gangguan berkelanjutan.
Meskipun ada larangan yang jelas, implementasinya sering kali lemah. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa banyak debt collector yang terlibat dalam praktik-praktik ini beroperasi di luar payung hukum, sering kali sebagai bagian dari “Pinjol ilegal”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2025 menemukan bahwa setidaknya setengah dari 227 platform Pinjol ilegal yang dilacak berbasis di China, yang membuat penegakan hukum menjadi sangat sulit. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak memadai dalam mengatur operasi lembaga penagihan utang itu sendiri. Ada ketiadaan badan sertifikasi resmi yang bertanggung jawab untuk memberikan lisensi dan standar etika bagi agensi penagihan, yang menciptakan “zona abu-abu” di mana operasi mereka tidak sepenuhnya terdaftar atau diawasi secara ketat. Hal ini memungkinkan agensi-agensi tersebut untuk menetapkan standar mereka sendiri, yang sering kali lebih berorientasi pada hasil (pengumpulan utang) daripada pada perlindungan konsumen.
Struktur insentif juga memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan metode yang lebih brutal. Bagus, seorang mantan kepala recovery di sebuah perusahaan leasing yang kini menjadi pengacara di Surakarta, mengungkapkan bahwa banyak debt collector dipekerjakan dengan model bayaran yang berbasis kinerja, di mana mereka dibayar per unit utang yang berhasil dikumpulkan atau disita. Model insentif ini menciptakan tekanan finansial yang besar bagi para penagih untuk menggunakan metode yang paling efektif dan cepat, yang sering kali sama dengan metode yang paling brutal dan intimidatif. Meskipun perusahaan mungkin memiliki instruksi formal untuk tidak menggunakan kekerasan, tekanan dari target kinerja sering kali mengalahkan peraturan internal tersebut.
Secara historis, Indonesia memiliki catatan panjang tentang kekerasan dalam penagihan utang. Pada tahun 2018, terdapat laporan bahwa debt collector di Jakarta telah menculik seorang gadis remaja berusia 14 tahun karena orang tuanya gagal membayar cicilan motor. Insiden ini menunjukkan adanya preseden untuk taktik intimidasi ekstrem yang ditujukan kepada keluarga debitur. Insiden tersebut bahkan menjadi salah satu pemicu reformasi regulatori yang lebih ketat pada tahun 2011, yang mengubah cara bank-bank menangani penagihan utang dan membatasi peran kolektornya. Namun, evolusi dari penagihan bank ke penagihan oleh platform Pinjol ilegal dan agensi swasta yang tidak terdaftar telah menciptakan kembali lingkungan di mana kekerasan dan intimidasi menjadi praktik yang lebih umum dan diterima.
Sebagai kesimpulan, metodologi penagihan utang yang digunakan di Jakarta sering kali dirancang untuk merusak hubungan sosial korban. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti penghinaan publik, ancaman terhadap identitas dan pekerjaan, dan pelanggaran privasi yang ekstrem, para penagih tidak hanya mencoba memaksa pembayaran, tetapi juga secara efektif membuat korban merasa terisolasi dan putus asa. Lingkungan sosial yang diciptakan oleh metode-metode ini, ditambah dengan kesenjangan regulasi dan insentif finansial yang mendorong kekerasan, menciptakan kondisi yang subur bagi eskalasi konflik dan kekerasan fisik, seperti yang terlihat dalam insiden Kalibata.
Kesenjangan Regulasi dan Struktur Instrinsik yang Memfasilitasi Kekerasan
Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan yang secara teoretis melarang praktik penagihan utang yang tidak etis dan kekerasan, kenyataannya menunjukkan adanya kesenjangan regulasi yang signifikan dan struktur instrinsik yang sering kali memfasilitasi perilaku buruk. Ekosistem penagihan utang di Jakarta beroperasi dalam sebuah “zona abu-abu” yang diisi oleh celah hukum, inkompabilitas antar-peraturan, dan insentif finansial yang mendorong kebrutalan. Memahami dinamika ini adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang, karena regulasi yang ada sering kali gagal mengikuti evolusi industri fintech dan Pinjol ilegal, serta tidak secara efektif mengatasi akar masalah yang mendorong kekerasan.
Salah satu kesenjangan regulasi yang paling fundamental adalah ketiadaan peraturan spesifik yang mengatur operasi lembaga jasa penagihan utang itu sendiri. Meskipun penagihan oleh lembaga jasa keuangan (seperti bank atau multi-finance company) diatur oleh peraturan seperti Bank Indonesia Regulation No. 23/2021 dan OJK Regulation No. 05/2022, tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur badan usaha yang menyediakan layanan penagihan sebagai pihak ketiga. Hal ini menciptakan ketidakjelasan mengenai otoritas yang berwenang untuk memberikan lisensi atau sertifikasi, serta institusi mana yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan standar etika bagi para penagih. Akibatnya, banyak agensi penagihan beroperasi tanpa lisensi resmi, memungkinkan mereka untuk menetapkan standar mereka sendiri yang sering kali lebih berorientasi pada hasil daripada pada perlindungan konsumen. Ketidakjelasan ini adalah fondasi dari deficit akuntabilitas dan pelanggaran terhadap konsumen.
Regulasi yang ada sering kali bersifat fragmentaris dan tidak komprehensif. Aturan-aturan ini tersebar di berbagai departemen dan lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Departemen Hukum dan HAM. Misalnya, Paylater provider dioperasikan di bawah tiga kerangka kerja regulasi yang berbeda: FSA Regulation 10/2022 untuk Platform Teknologi Berbasis Dana Bersama (LPBBTI), FSA Regulation 35/2018 untuk Perusahaan Pembiayaan, dan BI Regulation 23/2021 yang mengklasifikasikannya sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Setiap kerangka kerja memiliki obligasi kepatuhan, persyaratan lisensi, dan batasan penegakan yang berbeda, yang menciptakan ruang untuk ambiguitas dan celah di mana praktik-praktik buruk dapat bersembunyi. Selain itu, banyak dari peraturan ini dikeluarkan untuk industri tradisional dan belum sepenuhnya mengantisipasi kecepatan dan skalabilitas platform digital, terutama Pinjol ilegal.
Celah regulasi yang paling sulit diatasi adalah yang diciptakan oleh maraknya Pinjol ilegal. Sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global, OJK mulai mengizinkan model Peer-to-Peer (P2P) lending atau LPBBTI pada tahun 2016. Namun, regulasi ini, seperti OJK Regulation No. 40/2024, mensyaratkan bahwa platform hanya boleh bertindak sebagai perantara, melarang mereka mengelola dana secara langsung dan mewajibkan penggunaan agen penitipan pihak ketiga. Meskipun demikian, banyak operator ilegal yang menyalahgunakan model ini. Pada tahun 2024, OJK menerima 16.231 keluhan terkait entitas jasa keuangan ilegal, dengan 15.162 keluhan terkait Pinjol. Masalahnya diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar Pinjol ilegal ini berbasis di luar negeri, terutama di China, yang membuat penegakan hukum internasional menjadi sangat sulit. Pada Juli 2025, OJK bahkan mengidentifikasi bahwa setidaknya setengah dari 227 Pinjol ilegal yang dilacak berbasis di China. Regulasi domestik sering kali tidak berdaya melawan entitas yang beroperasi di luar yurisdiksi hukum Indonesia.
Selain kesenjangan regulasi, struktur instrinsik dalam industri penagihan juga memainkan peran krusial dalam memicu kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh Bagus, mantan kepala recovery, banyak debt collector dipekerjakan dengan model bayaran berbasis kinerja, di mana mereka dibayar per unit utang yang berhasil dikumpulkan atau disita. Model insentif ini menciptakan tekanan finansial yang sangat besar bagi para penagih untuk menggunakan metode yang paling efektif dan cepat, yang sering kali sama dengan metode yang paling brutal dan intimidatif. Meskipun perusahaan mungkin memiliki instruksi formal untuk tidak menggunakan kekerasan, tekanan dari target kinerja sering kali mengalahkan peraturan internal tersebut. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana kebrutalan menjadi strategi bisnis yang rasional bagi beberapa entitas untuk memaksimalkan profitabilitas.
Struktur hukum di Indonesia juga memiliki ambiguitas yang dapat dieksploitasi. Historisnya, sistem parate executie dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia memungkinkan kreditur untuk menyita aset tanpa perlu melalui proses pengadilan jika debitur gagal bayar. Meskipun Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 menghapuskan bagian ini dan menuntut keterlibatan pengadilan, praktik-praktik yang mirip masih terjadi. Petisi yang mendorong reformasi ini berasal dari dua debitur yang mengalami penyitaan kendaraan mereka secara paksa dan tanpa dokumentasi oleh kolektor utang, sebuah insiden yang menunjukkan bagaimana praktik-praktik keras ini telah menjadi bagian dari budaya penagihan sebelumnya. Saat ini, meskipun hukum telah berubah, banyak kolektor tetap menggunakan taktik intimidasi dan penyitaan paksa di jalan raya, seperti yang terjadi dalam kasus Kalibata, karena mereka mengetahui bahwa penegakan hukum sering kali lambat dan tidak konsisten.
Lebih jauh lagi, ada masalah dengan implementasi dan penegakan hukum yang ada. Meskipun ada banyak peraturan yang melarang kekerasan dan ancaman, penegakannya sering kali lemah. OJK menerima ribuan keluhan setiap tahun, tetapi sering kali gagal memberikan respons yang memuaskan. Meskipun OJK menerapkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, perintah, dan denda kepada penyedia jasa keuangan yang melanggar, sanksi ini sering kali tidak cukup untuk memberikan efek jera, terutama bagi entitas ilegal yang beroperasi di luar yurisdiksi. Sanksi pidana yang lebih berat, seperti hukuman penjara 2-10 tahun dan denda Rp 25 miliar hingga Rp 250 miliar yang diatur dalam UU PPSK, sering kali sulit diterapkan karena kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, terutama yang berbasis di luar negeri.
Sebagai kesimpulan, ekosistem penagihan utang di Jakarta dibiayai oleh kesenjangan regulasi yang mendalam dan struktur instrinsik yang sering kali mempromosikan perilaku buruk. Ketidakjelasan dalam peraturan, inkompabilitas antar-lembaga, keberhasilan operasi Pinjol ilegal di luar negeri, model insentif yang mendorong kebrutalan, dan lemahnya penegakan hukum menciptakan lingkungan di mana kekerasan dan intimidasi tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang rasional bagi beberapa entitas. Solusi yang efektif tidak hanya terletak pada penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kolektor utang, tetapi juga pada reformasi regulasi yang komprehensif untuk mengatasi celah-celah ini dan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Pola Kekerasan Berulang: Perbandingan dengan Kasus Serupa di Jakarta
Insiden pengeroyokan dua debt collector di Kalibata pada 11 Desember 2025 bukanlah sebuah kejadian yang unik atau anomal. Sebaliknya, insiden tersebut berfungsi sebagai puncak dari gunung es kekerasan dan konflik yang telah lama menjadi bagian dari lanskap penagihan utang di Jakarta. Analisis terhadap kasus-kasus serupa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mengungkapkan pola-pola yang berulang, yang menyoroti bahwa insiden Kalibata adalah manifestasi ekstrem dari dinamika konflik yang sudah mapan. Pola ini biasanya dimulai dengan pelanggaran prosedur penagihan yang jelas, yang kemudian memicu reaksi emosional dan fisik dari korban atau kerabatnya, yang berpotensi mengarah pada kerusuhan massal dan kerusakan properti.
Salah satu kasus yang paling menonjol dan relevan adalah insiden yang melibatkan selebriti Instagram (celebgram) SC pada 23 Februari 2023. Dalam insiden ini, sekitar 30 debt collector dari sebuah perusahaan jasa penagihan masuk ke apartemen SC di Jakarta Selatan secara paksa, mengambil kunci mobilnya dan menggunakan kata-kata kasar saat seorang polisi mencoba melakukan mediasi. Aksi paksa ini memicu kemarahan massa yang hadir di sekitar lokasi, yang kemudian melempari para kolektor dengan berbagai benda, termasuk batu. Insiden ini secara langsung memicu intervensi dari pihak berwenang, di mana Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Jakarta Selatan memerintahkan penangkapan segera terhadap para pelaku. Kasus Shinta Clara menunjukkan bagaimana interaksi fisik antara kolektor utang dan masyarakat sering kali menjadi percikan api yang memicu kerusuhan massal, di mana kehadiran polisi kadang-kadang terlambat atau tidak cukup untuk mencegah eskalasi.
Contoh lain yang menyoroti metode penagihan paksa di tempat umum adalah kasus yang terjadi di Bekasi pada Maret 2025. Dalam insiden ini, seorang remaja berusia 19 tahun bernama ARP (19) dikelilingi oleh beberapa orang tak dikenal di pusat perbelanjaan Juanda, diminta secara paksa untuk menandatangani surat serah terima kendaraan, dan kemudian mobilnya dicabut dan dibawa pergi. Aksi ini terjadi di luar jam kerja dan prosedur yang diatur oleh OJK, menunjukkan betapa tidak terkontrolnya praktik penagihan paksa di tempat umum yang ramai. Kasus ini juga menyoroti bagaimana pelaku sering kali tidak memiliki sertifikasi, surat penugasan, atau otoritas hukum yang sah, sebuah praktik yang juga diamati dalam kasus Kalibata.
Kekerasan tidak hanya terjadi dalam konteks individu versus kolektor, tetapi juga antara entitas bisnis. Kasus PT RPM vs PT BLI pada 3 Maret 2025 menunjukkan bahwa kekerasan fisik juga dapat terjadi dalam skala bisnis-bisnis besar. Dalam insiden ini, dua perwakilan tingkat tinggi dari perusahaan distributor makanan PT RPM mengalami pemukulan, ancaman kematian, dan ancaman terhadap keluarga mereka selama pertemuan penyelesaian utang di sebuah restoran di Kebayoran Baru, South Jakarta. Peristiwa ini berlangsung selama sekitar tiga jam dan terjadi setelah perusahaan debitur, PT BLI, menunda pembayaran utang sebesar Rp6,2 miliar yang telah disepakati. Kasus ini menggarisbawahi bahwa di balik fasad bisnis yang profesional, kekerasan fisik dapat menjadi alat penyelesaian sengketa utang antar-perusahaan, yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak terbatas pada penagihan konsumen.
Selain konflik langsung antara kolektor dan debitur/massa, terdapat pula bentrokan antar-kelompok sipil yang melibatkan kolektor utang. Insiden yang terjadi di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, adalah contoh dari bentrokan fisik antara organisasi masyarakat (ormas) dengan sekelompok debt collector. Konflik ini dipicu oleh kesalahpahaman dan berawal dari serangan dari salah satu kelompok, yang melibatkan pelemparan batu dan benda tumpul lainnya. Meskipun insiden ini tidak mengakibatkan korban jiwa, ia menimbulkan kegaduhan yang signifikan di kalangan warga sekitar. Kepolisian terpaksa ikut campur untuk memediasi konflik, dan pada akhirnya, kedua kelompok berhasil damai dan berada dalam kondisi yang kondusif. Bentrokan ini menunjukkan bahwa kolektor utang dapat menjadi pemicu konflik antar-kelompok masyarakat yang tidak melibatkan intervensi polisi sebagai mediator netral, menciptakan situasi di mana kekerasan dapat dengan mudah menyebar.
Perbandingan antara kasus-kasus ini mengungkapkan beberapa pola kunci:
- Awal yang Dimulai dengan Pelanggaran Prosedur: Hampir setiap insiden kekerasan dimulai dengan tindakan kolektor yang melanggar SOP yang jelas. Ini bisa berupa penyitaan paksa di jalan raya (Kalibata), masuk paksa ke properti pribadi (Shinta Clara), penarikan paksa di tempat umum (Bekasi), atau penggunaan kekerasan fisik dalam pertemuan bisnis (PT RPM vs PT BLI). Pelanggaran ini sering kali menjadi titik awal yang memicu reaksi emosional.
- Reaksi Emosional dan Fisik Massa: Ketika kolektor terlihat melanggar hukum atau menunjukkan kebrutalan, reaksi dari debitur, kerabat, atau massa yang hadir sering kali bersifat impulsif dan fisik. Mereka tidak lagi melihat kolektor sebagai individu yang sedang menjalankan tugas, tetapi sebagai agen dari sistem yang menindas.
- Eksploitasi oleh Aparat Negara: Dalam beberapa kasus, seperti insiden Kalibata, aparat negara (polisi) sendiri menjadi agen kekerasan, baik sebagai pemicu awal (Brigadir AM) maupun sebagai pihak yang gagal mencegah eskalasi. Ini menunjukkan adanya regresi hukum dan potensi kolusi atau toleransi terhadap praktik-praktik ilegal.
- Eskalasi Menuju Kerusuhan Massal dan Kerusakan Properti: Setelah konfrontasi fisik terjadi, sering kali meluas menjadi kerusuhan massal yang melibatkan pembakaran dan perusakan properti milik warga sipil. Aksi pembalasan oleh rekan korban di Kalibata adalah contoh paling ekstrem dari pola ini, di mana kerugian materiil mencapai miliaran rupiah.
- Keterbatasan Penegakan Hukum: Meskipun ada banyak peraturan yang melarang kekerasan, penegakan hukum sering kali lemah, lambat, atau tidak konsisten. Hal ini membuat para pelaku merasa aman untuk terus beroperasi, bahkan dengan metode yang lebih brutal. Otoritas sering kali hanya bertindak setelah insiden besar terjadi, bukan mencegahnya.
Secara keseluruhan, analisis kasus-kasus serupa ini mengkonfirmasi bahwa insiden Kalibata bukanlah sebuah kejadian yang terpisah, melainkan merupakan puncak dari sebuah siklus konflik yang berulang. Pola-pola yang teridentifikasi—dimulai dengan pelanggaran prosedur, diikuti oleh reaksi emosional, eskalasi kekerasan, dan sering kali diperparah oleh intervensi atau kegagalan intervensi oleh aparat negara—menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik. Tanpa adanya perubahan fundamental dalam regulasi, praktik penagihan, dan penegakan hukum, kemungkinan besar kita akan terus melihat pola kekerasan yang sama berulang di masa depan.
Implikasi Sosial dan Rekomendasi untuk Masyarakat Umum
Analisis mendalam terhadap insiden pengeroyokan debt collector di Kalibata dan konteks sosial yang lebih luas di sekitarnya mengungkapkan serangkaian implikasi yang mendalam bagi masyarakat umum di Indonesia. Insiden ini bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan sebuah cerminan dramatis dari pergeseran sosial dan ekonomi yang sedang terjadi. Ia menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan, kerentanan finansial, dan celah dalam regulasi dapat berpadu untuk menciptakan lingkungan yang subur bagi kekerasan dan kerusakan. Oleh karena itu, bagi masyarakat umum, pemahaman terhadap implikasi ini sangat penting untuk melindungi diri, mengadvokasi perubahan, dan membangun komunitas yang lebih tangguh.
Implikasi pertama dan yang paling langsung adalah bahwa utang konsumtif, terutama dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi seperti Pinjol ilegal, bukan lagi hanya masalah finansial individu, melainkan sebuah risiko sosial yang nyata. Kasus-kasus seperti Nadhea Putri, yang meminjam uang untuk membeli ponsel dengan nilai lima kali lipat dari penghasilannya, dan Maisaroh, yang terperosok ke dalam utang puluhan juta rupiah setelah uang cicilan dialihkan untuk biaya medis, menggarisbawahi betapa mudahnya seseorang dapat terjebak dalam lingkaran setan utang. Risiko ini tidak hanya terbatas pada tekanan finansial, tetapi juga meluas ke ranah psikologis dan sosial. Debitur mengalami teror psikologis, stres, depresi, dan rasa malu yang mendalam, yang sering kali membuat mereka menyembunyikan utang dari keluarga dan teman terdekat mereka. Ini berarti bahwa utang konsumtif dapat merusak hubungan keluarga, persahabatan, dan bahkan karier profesional. Bagi masyarakat umum, implikasi ini adalah bahwa utang, terutama utang konsumtif, harus dilihat sebagai ancaman multidimensional yang dapat memicu konflik, kerusakan properti, dan kekerasan fisik yang tidak terduga.
Implikasi kedua adalah perlunya pergeseran persepsi terhadap debt collector. Meskipun banyak dari mereka yang menggunakan metode yang tidak etis dan merusak, mereka juga adalah orang-orang yang bekerja dan berisiko. Mengabaikan hak-hak mereka dan melihat mereka sebagai musuh yang sah untuk dilawan dapat menciptakan lingkungan di mana mereka menggunakan kekerasan sebagai alat profesional yang diterima. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah memastikan bahwa utang diselesaikan melalui jalur hukum yang benar, bukan melalui keadilan vigilante. Ketika masyarakat merasa frustrasi dengan kolektor, respons yang konstruktif adalah melaporkan pelanggaran mereka kepada OJK atau lembaga penegak hukum, bukan dengan membalas kekerasan. Namun, pada saat yang sama, masyarakat juga harus menyadari bahwa mereka tidak boleh menjadi target kekerasan atau intimidasi, dan harus mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen.
Implikasi ketiga adalah adanya kebutuhan mendesak untuk advokasi regulasi yang lebih kuat. Regulasi yang ada, meskipun banyak, sering kali gagal mengikuti evolusi industri fintech dan Pinjol ilegal, serta tidak secara efektif mengatasi akar masalah yang mendorong kekerasan. Bagi masyarakat umum, ini berarti bahwa partisipasi aktif dalam kampanye edukasi publik dan advokasi kebijakan menjadi sangat krusial. Masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkret berikut:
- Memperkuat Penegakan Hukum: Meningkatkan sanksi bagi debt collector ilegal dan memastikan penegakan hukum yang konsisten dan cepat terhadap mereka yang melanggar. Ini termasuk memperkuat kerja sama internasional untuk menargetkan Pinjol ilegal yang berbasis di luar negeri.
- Menetapkan Badan Sertifikasi Resmi: Menciptakan badan sertifikasi resmi yang bertanggung jawab untuk memberikan lisensi dan standar etika yang jelas bagi lembaga penagihan utang. Hal ini akan menghilangkan “zona abu-abu” saat ini dan meningkatkan akuntabilitas.
- Melindungi Korban Utang: Mendorong implementasi program restrukturisasi utang yang mudah diakses bagi masyarakat yang terganggu oleh utang, untuk memutus siklus “utang-trap” yang merusak.
- Edukasi Publik: Meluncurkan kampanye edukasi publik yang masif tentang hak-hak konsumen dalam utang, cara-cara yang benar untuk menyelesaikan sengketa, dan pentingnya literasi finansial. Edukasi ini harus mencakup cara-cara yang benar untuk menyelesaikan sengketa utang.
Sebagai kesimpulan, insiden Kalibata adalah sebuah peringatan keras bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan, kerentanan finansial, dan celah dalam regulasi dapat berpadu untuk menciptakan lingkungan yang subur bagi kekerasan dan kerusakan. Solusi jangka panjang tidak hanya terletak pada penegakan hukum yang lebih ketat terhadap debt collector, tetapi juga pada pembangunan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat, literasi finansial yang lebih luas, dan regulasi yang lebih adaptif dan efektif. Bagi masyarakat umum, tanggung jawab ini tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga urusan kolektif untuk membangun komunitas yang lebih tangguh, inklusif, dan beradab dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.