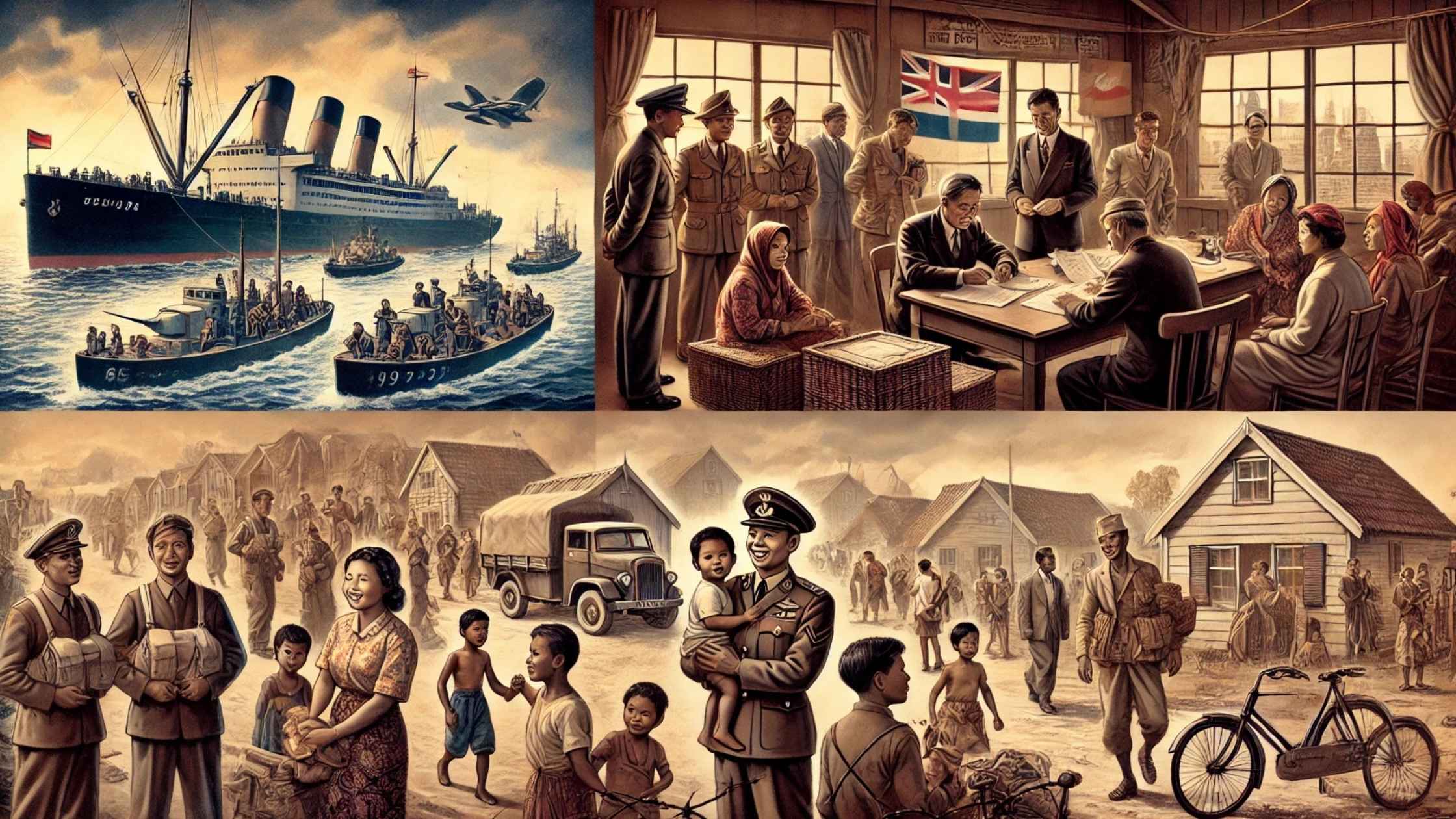Tujuh puluh tahun yang lalu, ribuan orang Maluku tiba di Belanda—sebuah perjalanan yang mereka tempuh bukan karena keinginan, tetapi karena keadaan sejarah yang memaksa. Mereka datang sebagai mantan tentara KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) dan keluarga mereka, meninggalkan tanah air yang dicintai dan memasuki dunia baru yang penuh ketidakpastian.
“Kami ingin bersatu untuk menceritakan sejarah kami.”
Tiga keturunan mereka berbagi kisah tentang komunitas mereka dan pandangan mereka terhadap sejarah.

“Generasi pertama orang Maluku kehilangan segalanya.”
Ichtus Rahanra (49) – Pegiat Pelestarian Permukiman Maluku
Saya adalah orang Maluku Tenggara. Belanda pertama kali menaklukkan Maluku Tengah—Ambon, Haruku, dan Saparua—sekitar 400 tahun yang lalu untuk mengambil rempah-rempah. Relatif banyak orang Maluku menjadi pegawai pemerintah dan guru dalam sistem administrasi Hindia Belanda, atau tentara dalam Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).
Namun, di kepulauan Tenggara, Belanda baru hadir pada awal abad ke-20, ketika mereka membutuhkan tentara. Hal ini membuka peluang bagi anak-anak muda yang sebelumnya hanya bisa menjadi petani.
Ayah saya, pada usia 18 tahun, bergabung dengan KNIL pada tahun 1939. Perjalanan ke Ambon saja sudah terasa seperti perjalanan keliling dunia baginya. Setelah itu, ia bertugas di seluruh Nusantara—Sumatra, Jawa, Kalimantan—hingga akhirnya Jepang menyerang pada tahun 1942.
Bagi Jepang, orang Maluku secara kolektif dianggap pro-Belanda. Saat itu, ayah saya sedang cuti ketika Jepang menangkapnya dan menahannya di kamp hingga tahun 1945. Banyak orang Maluku yang ditangkap di Jawa dan Sumatra dikirim untuk bekerja di jalur kereta Burma yang terkenal kejam.
Ayah saya selalu berkata, “Saya juga mendapat pukulan, tetapi saya masih beruntung. Di seberang pagar, yang menyiksa kami adalah orang-orang kita sendiri.”
Ketika Jepang kalah, ayah saya kembali bergabung dengan KNIL dan ditempatkan di Jawa. Itu adalah masa Bersiap, awal dari perang kemerdekaan Indonesia yang penuh kekacauan, dimana kekejaman terjadi di kedua belah pihak.
Ayah saya, seperti banyak lainnya, jarang berbicara tentang masa tugasnya di Jawa antara 1945 hingga 1951. Namun, saya sering mendengar dia berteriak saat bermimpi buruk, hingga ibu saya harus membangunkannya.
Saya tidak menyalahkan para ayah kami—saya tidak tahu bagaimana saya sendiri akan bertindak dalam situasi perang seperti itu. Saya sangat menghormati kemampuan mereka untuk bertahan hidup, sesuatu yang mereka wariskan kepada kami. Kepercayaan mereka adalah pegangan hidup mereka. Hidup mereka adalah bertahan, dan generasi muda sekarang menikmati hasil dari perjuangan mereka.
Tiba di Belanda: Kehidupan dalam Kamp-Kamp Penampungan
Ayah saya tiba di Belanda pada 8 April 1951 dengan kapal Roma, yang merupakan kapal ketiga yang membawa orang Maluku ke Belanda. Dia ditempatkan di kamp Amersfoort, dimana ia menerima pemecatan dari militer, seperti banyak orang Maluku lainnya, tanpa mendapatkan pensiun.
Setelah itu, ia dipindahkan ke kamp dekat Steenwijk, kemudian ke keluarga asuh di Rotterdam, sebelum akhirnya bergabung dengan komunitas Maluku Tenggara di kamp dekat Ommen.
Di Hindia Belanda, kebijakan “divide et impera” (pecah belah dan kuasai) oleh Belanda telah menciptakan ketegangan antara orang Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Namun, di Belanda, mereka ditempatkan dalam kamp yang sama, menyebabkan konflik meledak di Kamp Vught pada tahun 1951.
Akibatnya, komunitas Maluku Tenggara dipisahkan ke kamp yang berbeda, dan kemudian ke pemukiman yang terpisah.
Peristiwa kekerasan ini harus dilihat dalam konteks waktu itu. Mereka hidup dalam kondisi “lockdown” dari 1949 hingga 1956—pertama di kamp-kamp di Jawa, kemudian di kamp-kamp di Belanda. Wajar jika ketegangan meningkat.
Kini, pada tahun 2021, saya ingin meninggalkan masa lalu itu, dan bersatu sebagai orang Maluku untuk menceritakan sejarah kami.
Saya tumbuh di permukiman Maluku di Zwolle. Kami bermain dengan anak-anak Belanda, bersekolah di sekolah yang sama, dan mengalami masa kecil yang indah. Sekarang, saya aktif di Rijssen, sebagai anggota organisasi yang memperjuangkan pelestarian permukiman Maluku.
Ketika kamp-kamp di Belanda ditutup pada tahun 1956, pemerintah berjanji bahwa orang Maluku akan mendapatkan rumah mereka sendiri. Selama orang Maluku masih ingin tinggal di sana, mereka harus bisa melakukannya. Ini adalah sesuatu yang menyatukan kita—rasa sakit orang tua kami terukir dalam tempat tinggal kita.
Generasi pertama kehilangan segalanya. Tapi ini, rumah kita, tidak akan kita biarkan diambil dari kita.
“Mungkin jika aku hidup di tahun 70-an, aku juga akan menjadi pembajak kereta.”
Geronimo Matulessy (37) – Fotografer dan Aktivis RMS
Saya lahir di permukiman Maluku di Bemmel. Ketika saya berusia empat tahun, saya menyaksikan ayah saya dibunuh oleh kenalan Maluku sendiri.
Trauma ini membuat saya menolak akar budaya saya selama bertahun-tahun.

Saya dibesarkan oleh ibu saya, yang kemudian menikah dengan pria Belanda. Saat kecil, saya tinggal di Apeldoorn, di lingkungan kelas menengah. Teman saya pernah berkata, “Kamu memang orang Maluku, tapi kamu Maluku yang baik.”
Ketertarikan saya pada perjuangan Maluku baru muncul pada 2013, ketika saya bertemu pasangan saya yang juga orang Maluku. Dia menghadapkan saya pada identitas yang selama ini saya tolak.
Saya mulai meneliti legalitas Republik Maluku Selatan (RMS), dan pada 2014, saya mengunjungi keluarga ibu saya di Maluku. Itu adalah pengalaman yang sangat emosional, seperti pulang ke rumah.
Kami generasi muda tidak dibebani dengan trauma seperti generasi sebelum kami. Namun, ketika saya berbicara dengan ibu saya tentang pembajakan kereta di Belanda dan jet tempur yang dikirim untuk menanganinya, air mata tetap mengalir di pipinya karena kemarahan dan frustrasi.
Saya bisa memahami kenapa generasi kedua memilih jalan kekerasan pada tahun 70-an. Mereka melihat orang tua mereka dikhianati, dicabut statusnya, dan dibuang ke kamp-kamp. Mereka menemukan kebenaran: “Kami telah ditipu selama berabad-abad.”
Hari ini, kita tidak lagi bertarung dengan kekerasan. Tapi kita harus jujur tentang sejarah kita.
Saya tidak menuntut Belanda untuk mengirim pesawat tempur ke Ambon, tetapi saya ingin mereka memenuhi kewajiban hukum mereka terhadap RMS.
Rakyat Maluku menderita dalam kemiskinan dan penindasan. RMS bisa menjadi solusi.
Namun, bagaimana bisa kita tahu apa yang diinginkan rakyat Maluku, jika mereka tidak bisa mengibarkan bendera RMS tanpa ditangkap?
Biarkan rakyat Maluku memutuskan nasib mereka sendiri.
Jika mereka menolak RMS, maka saya akan menerima itu.
Tapi beri mereka kesempatan untuk memilih.

“Kakek dan Nenek Saya Sebenarnya Tercerabut dari Akar Mereka Sepanjang Hidup”
Yayah Siegers-Samaniri (46) – Pegiat Komunitas Muslim Maluku di Belanda
Keluarga ayah saya berasal dari desa Muslim di Ambon.
Sangat tidak biasa bagi seorang Muslim untuk bertugas di KNIL, karena umumnya tentara KNIL berasal dari komunitas Kristen Maluku. Di Belanda, hanya sekitar seribu orang Maluku yang beragama Islam, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan komunitas Maluku secara keseluruhan.
Kakek saya sudah bertugas di KNIL bahkan sebelum Perang Dunia II. Saya pernah bertanya kepadanya mengapa ia memilih menjadi tentara, tetapi ia tidak pernah banyak bercerita. Ia hanya berkata bahwa ia membutuhkan pekerjaan dan tertarik untuk mengenal bagian lain dari Indonesia.
Pada tahun 1951, ia harus memilih: bergabung dengan tentara Indonesia atau pindah ke Belanda. Saat itu, ia sudah menikah dengan nenek saya, seorang perempuan Muslim dari Jakarta.
Nenek saya takut akan tindakan balas dendam terhadap keluarga mereka jika mereka tetap tinggal di Indonesia. Akhirnya, mereka berangkat ke Belanda bersama anak mereka—ayah saya.
Tiba di Belanda: Hidup di Kamp Penampungan
Begitu tiba di Belanda, kakek saya langsung diberhentikan dari dinas militer.
Mereka pertama kali ditempatkan di Schattenberg, sebuah kamp yang sebelumnya digunakan sebagai kamp konsentrasi Westerbork pada masa perang.
Seandainya para penghuni kamp ini adalah pendeta atau guru, maka mungkin dinamika di sana akan berbeda. Namun, mereka adalah mantan tentara, orang-orang yang telah kehilangan segalanya dan tiba-tiba harus berjuang bertahan hidup di negeri yang asing dan dingin.
Bayangkan jika para tentara Dutchbat yang mengalami trauma perang di Bosnia dipulangkan ke Belanda bersama keluarga mereka dan kemudian ditempatkan di kamp isolasi—apa yang akan terjadi?
Pada tahun 1953, terjadi insiden besar di Schattenberg, yang dikenal sebagai “Insiden Dapur”.
Seorang tentara Maluku Kristen secara tidak sengaja mengaduk nasi milik tentara Muslim dengan sendok yang sebelumnya digunakan untuk mengambil daging babi.
Peristiwa ini memicu ketegangan yang serius. Kakek saya, yang menyaksikan langsung kejadian ini, sering bercerita tentang betapa marah dan tersinggungnya komunitas Muslim Maluku.
Setelah insiden itu, komunitas Muslim menuntut kamp terpisah. Akhirnya, pada tahun 1954, mereka dipindahkan ke kamp baru di Balk, Friesland, yang diperuntukkan khusus bagi komunitas Muslim Maluku.
Ayah saya tinggal di kamp selama 16 tahun, dan baru pindah ke Ridderkerk ketika ia berusia lebih dari 20 tahun. Di sana, ia menyelesaikan studinya sebagai arsitek teknik sipil.
Ibu saya bukan keturunan Maluku. Ia berasal dari Indonesia dan datang ke Belanda sebagai perawat melalui program pertukaran pelajar pada tahun 1970-an.
Saya sendiri dibesarkan oleh kakek dan nenek saya hingga saya mulai masuk sekolah dasar. Ini adalah sesuatu yang sering terjadi dalam budaya Maluku.
Namun, setelah itu, saya kembali tinggal bersama orang tua saya.
Identitas dan Warisan Islam di Komunitas Maluku
Saya tidak dibesarkan dengan ideologi RMS (Republik Maluku Selatan).
Di komunitas Maluku, RMS sering dikaitkan dengan kelompok Kristen, dan bahkan ada lelucon bahwa huruf “S” dalam RMS berarti “Serani” (Kristen).
Di Ridderkerk, komunitas Maluku Muslim tidak memiliki permukiman sendiri. Kami ditempatkan di antara masyarakat Belanda, dan ternyata hasilnya cukup positif.
Generasi berikutnya berhasil dalam dunia kerja dan pendidikan, lebih baik dibandingkan mereka yang tumbuh di lingkungan Maluku yang lebih tertutup.
Pada tahun 1984, pemerintah Belanda memberikan sebuah bangunan untuk komunitas Muslim Maluku yang kemudian diubah menjadi masjid.
Pemberian ini dianggap sebagai bentuk “kompensasi”, karena komunitas Maluku Kristen sudah lebih dulu mendapatkan gereja mereka sendiri.
Kembali ke Indonesia dan Perasaan Tercerabut dari Akar
Ketika kakek dan nenek saya sudah lanjut usia—di usia 60-an—mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta setelah hampir 40 tahun tinggal di Belanda.
Awalnya, mereka sangat menikmati kepulangan mereka.
Namun, seiring waktu, mereka menyadari bahwa “rumah” bukan hanya sekadar tanah kelahiran.
Ketika mereka mulai membutuhkan perawatan dan bantuan, mereka menyadari bahwa anak-anak dan cucu mereka tetap tinggal di Belanda.
Pada akhirnya, mereka merasakan kesepian dan keterasingan yang mendalam.
Mereka telah tercerabut dari akar mereka sepanjang hidup mereka.
Sekarang, saya aktif di Dewan Masjid Maluku di Ridderkerk, tempat ayah saya sebelumnya menjabat sebagai ketua selama 17 tahun.
Di Indonesia, perempuan sering terlibat dalam organisasi keagamaan Islam, dan saya ingin mempertahankan tradisi itu di Belanda.
Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga warisan budaya Maluku yang harus kita pertahankan.
Namun, di masjid kami, semua orang diterima.
Orang-orang dari Maroko, Suriah, Afghanistan, Somalia, dan Suriname juga ikut beribadah di sana.
Keramahan dan keterbukaan terhadap orang lain adalah nilai utama dalam budaya Maluku, dan itulah yang ingin saya terus jaga.
Kesimpulan: Perjuangan dan Identitas Orang Maluku di Belanda
Tujuh puluh tahun setelah generasi pertama orang Maluku tiba di Belanda, kisah mereka tetap relevan.
Mereka kehilangan tanah air, status, dan identitas mereka, tetapi mereka juga mewariskan semangat bertahan hidup yang luar biasa kepada generasi berikutnya.
Hari ini, komunitas Maluku di Belanda masih mencari cara untuk memperjuangkan warisan mereka, menyuarakan sejarah mereka, dan mempertahankan identitas mereka dalam masyarakat yang terus berubah.
Artikel ini menggambarkan kisah nyata perjuangan, kehilangan, dan ketahanan generasi pertama orang Maluku di Belanda. Jika Anda ingin lebih memahami perjalanan sejarah mereka, diskusi lebih lanjut sangatlah penting.
Penulis: Eric Brassem
Fotografer: Martijn Gijsbertsen
“De eerste generatie Molukkers is alles afgepakt: 70 jaar later interviews”